Untuk membaca Part-1 silakan klik sini.
Keponakan
Pak Amrialis masuk dengan membawa nampan berisi tiga cangkir teh. Sinar curiga
sudah berlalu dari kedua matanya. Ia mempersilakan kami minum lalu duduk di
lantai tak jauh dari ruang tamu. Agaknya, perempuan yang sepertinya seusia saya
itu juga penasaran dengan apa yang kami perbincangkan.
“Tentang
lahan yang dulu itu, bagaimana kelanjutannya, Pak? Saya minta maaf, waktu itu
tidak ikut mendampingi sampai selesai.” Ucap saya sedikit menyesal.
“Ndak ado kelanjutan yang menggembirakan,
nak. Masyarakat terpaksa merelakan lahannyo
dengan ganti rugi sangat kecil. Siapo
berani melawan, kalau tiap hari yang datang itu preman-preman? Alasannyo untuk menjaga keamanan. Tetapi, yang
mereka lakukan adalah intimidasi sampai kami menyerah.”
Pak Amrialis
menarik napas dalam-dalam. Menatap kejauhan dengan sorot mata layu.
“Kalau
begitu, lahan yang sekarang menjadi sumber titik api itu sebenarnya adalah
milik perusahaan, dan masyarakat yang membakar juga adalah atas perintah
perusahaan.” Saya berkonklusi.
Pak Amrialis
mengangguk. “Begitulah, nak. Ayo diminum dulu, nanti baunyo bercampur asap.”
Saya
tersenyum kecut. Melihat lelaki tua ini yang masih mencoba berguyon di tengah
kepedihannya. Masih terbayang dalam benak saya, bagaimana tiga tahun dulu dia
berusaha mengumpulkan tanda tangan semua warga untuk menolak ganti rugi. Usahanya
berakhir gagal. Dan sekarang, lagi-lagi masyarakat kecil seperti Pak Amrialis harus
menjadi tumbal untuk melepaskan pelaku yang sebenarnya dari jeratan hukum.
Bim Bim memberi isyarat dengan anggukan,
pertanda sudah saatnya kami harus berpamitan. Saya menggeser duduk ke arah Pak Amrialis,
menatap pria tua ini sungguh-sungguh.
“Kali
ini saya tidak berani menjanjikan apa-apa, Pak. Persoalan ini terlalu kompleks.
Tetapi, saya dan Mercusuar akan berusaha semaksimal yang kami bisa. Setidaknya, orang-orang di
luar sana harus tahu siapa sesungguhnya dalang dibalik pembakaran ini dan tidak
gampang percaya dengan omongan pihak-pihak yang menyudutkan masyarakat kecil.”
Pak Amrialis
menundukkan kepala. Wajahnya tampak letih dan juga pasrah. “Semoga usaha kalian
diberkati Tuhan, Nak. Tetapi saya minta tolong, jangan nama saya disebut-sebut dalam
koran. Saya hanya ingin hidup tenang dan tetap bisa bernapas sampai kabut asap
ini ndak ado lagi.”
**************
Saya hanya ingin hidup tenang dan tetap
bisa bernapas sampai kabut asap ini ndak ado lagi.
Kata-kata
terakhir Pak Amrialis masih terngiang di telinga saya. Sungguh. Harapannya tidak
sesederhana apa yang terucap. Siapa bisa memastikan kapan kabut asap ini
benar-benar akan sirna? Kalaupun kedatangan musim hujan nanti akan memadamkan
semua titik api dan mengembalikan warna langit, siapa bisa menjamin bahwa
pembakaran hutan akan benar-benar berhenti?
Dalam
kondisi seperti ini, banyak orang berkata kalau Tuhan sedang murka. Sedikit
saja yang percaya bahwa inilah sesungguhnya cara Tuhan mendidik manusia untuk
tak lagi merusak alamNya.
“Melamun
terus. Apa yang kamu pikirkan?” Pertanyaan Bim Bim memecah kesunyian yang tercipta
sejak kami meninggalkan rumah Pak Amrialis. Bim Bim mengendarai mobil dengan
kecepatan 60 km/jam. Di luar sana, jalan raya dan sekelilingnya tak ubahnya seperti
kota hantu. Kabut gelap telah kian memperpendek jarak pandang. Dari kaca spion,
kami hanya mampu melihat kendaraan yang berada
persis di belakang mobil. Selebihnya, hanya pendar cahaya lampu yang
susul menyusul dalam gerak lambat yang mampu tertangkap oleh mata.
“Banyak.
Sangat banyak.” Jawab saya seraya menatap lurus ke depan. “Kita tahu akan
faktanya, tetapi kita juga kesulitan mengumpulkan bukti yang bisa memperkuat
fakta itu. Dengan kondisi sekarang, sangat berat jika kita harus menemui satu
per satu warga pemilik lahan yang diganti rugi untuk bisa melihat bukti
kepemilikan tanah mereka yang telah dikuasai perusahaan.”
“Bagaimana
kalau kita meminta bantuan instansi berwenang? Kita cukup minta ditunjukkan sertifikat
lahan warga yang telah beralih ke perusahaan.”
Saya
tertawa sumbang. “Memangnya kamu pikir kita siapa, Bim? Kecuali jika kita pihak
kepolisian yang datang dengan surat resmi untuk melakukan penyelidikan.”
“Lantas,
kamu tetap mau mengangkatnya tanpa bukti yang valid?”
Saya
berpikir sejenak. “Data-data saat meliput kasus ganti rugi itu masih ada. Aku akan
menyajikan berita berdasarkan kronologis peristiwa dan membiarkan pembaca
menilai fakta mana yang lebih mendekati kebenaran.”
“Astaga,
jadi kamu mau menggunakan bahan basi untuk membuat makanan yang harus disajikan
sekarang?” Nada suara Bim Bim tiba-tiba meninggi.
Saya
menjawab dengan nada tak kalah tinggi. “Asal kamu tahu Bim, dokumen tentang hak
atas tanah tidak boleh dimusnahkan sampai usianya minimal mencapai 20 tahun!
Itu artinya, data tiga tahun lalu masih sangat valid. Apalagi proses ganti
ruginya sendiri baru benar-benar selesai awal tahun ini.”
Bim
Bim tak menjawab. Rekan saya ini hanya menoleh sekilas lalu mengedik bahu. Melanjutkan
sisa perjalanan kami yang kembali sunyi.
*****************
Saya
memutuskan untuk menulis di kolom essai Mercusuar. Tak sekadar fakta di
lapangan, saya juga menuliskan opini pribadi berdasarkan semua data dari
peristiwa lampau hingga kini. Sungguh. Menuliskan sesuatu yang menggabungkan
fakta dan analisa, rasanya tiga kali lebih berat dibandingkan dengan hanya
sekadar menyajikan berita.
Refrain
lagu Let It Go memekik dari ponsel saya. Nama Pak Haris muncul di layar.
“Halo,
Retni, apa kabar?”
“Alhamdulillah,
baik Pak.”
“Syukurlah.
Bagaimana perkembangan terakhir?”
Saya
melaporkan semuanya dengan singkat dan to
the point termasuk kabar tentang kondisi cuaca hari ini. Pak Haris tengah
berada di Jakarta, menghadiri undangan Kementerian Kehutanan yang menjelaskan kebijakan
pemerintah sekarang atas kondisi pasca pembakaran hutan.
Di
ujung sana, saya mendengar bunyi napas berat Pak Haris setelah saya selesai
berbicara.
“Kenapa
kamu malah ingin menulis essai? Kamu tahu ‘kan berapa persen pembaca kita yang
mau membaca kolom itu?”
“Tetapi
data-data terbaru yang saya kantongi masih minim, Pak. Apa yang dapat saya simpulkan,
masyarakat pemilik lahan memilih untuk bungkam dan instansi terkait juga tidak
mau sembarangan membeberkan dokumen tanah dimaksud.”
Hening
sesaat. Suara Pak Haris baru terdengar lagi beberapa detik kemudian. “Kalau
begitu, kita tetap akan menampilkannya di lembar pertama, tetapi di kolom
terbawah yang biasa diisi untuk feature.
Kita bagi dalam dua kali pemuatan. Tetap pertahankan opini netral dan
proporsional. Ingat, Retni. We must be
part of solution, not part of problem.”
“Baik,
Pak.”
Saya
bangkit menuju dapur dan mengisi air dalam coffee-maker
setelah pembicaraan kami selesai. Sepertinya, saya butuh minimal dua cangkir
kopi untuk menemani saya menuntaskan tulisan ini malam ini.
************
Saya
terjaga oleh bunyi keras yang menampar-nampar kaca jendela. Awalnya saya pikir
angin kencang tengah bertiup dan seperti biasa, menerbangkan debu-debu
berjelaga ke segala arah. Namun saat saya memandang ke arah jendela dan
menajamkan telinga, mata saya spontan terbelalak. Ini hujan!
Saya
berlari menuju jendela dan menempelkan wajah di kaca. Alhamdulillah! Ini memang
hujan!
Saya
telah tertidur begitu lelapnya setelah semalaman menyelesaikan artikel yang
saya janjikan pada Pak Haris. Senyum saya merekah saat sejenak mengecek linimasa
twitter yang telah penuh dengan twit kesyukuran disertai tagar
#Pekanbaruakhirnyahujan.
Saya
merentangkan tangan tinggi-tinggi. Meregangkan tubuh yang seakan remuk. Saya
menatap langit. Untuk kali pertama sejak dua bulan ini, langit kota ini
menunjukkan sedikit senyumnya.
Mendadak,
saya teringat sesuatu. Hujan memang selalu punya kekuatan magis untuk
meresonansi masa lalu. Saya terpejam. Dalam sekejap, kenangan itu kembali
mengepung saya. Kenangan akan sebait nama dan sekelebat peristiwa bersamanya di
Tesso Nilo.
************
Hujan
deras mengiringi perjalanan saya menuju Taman Nasional Tesso Nilo. Dalam
situasi normal, seharusnya perjalanan ini tuntas dalam tempo lima jam. Namun
dengan kecepatan yang tidak bisa melebihi 60 km/jam, perjalanan harus saya tempuh
dalam waktu kurang lebih tujuh jam.
Hujan
deras telah berganti gerimis saat saya memarkir mobil di tepi jalan. Aroma
tanah yang menguapkan hawa panas menyambut saya saat turun dari mobil. Pak
Tungkat, seorang warga desa yang menjadi pemandu saat kedatangan pertama saya
dulu, datang menghampiri saya lima menit kemudian. Saya telah menelponnya
sebelumnya dan memintanya meminjamkan sepeda motor untuk saya kendarai menuju
taman nasional itu.
“Adik
ndak apo-apo bawa motor sendiri? Selepas hujan, medannyo licin dan sulit.” Ujar Pak Tungkat.
Saya menggeleng. “Ndak apo-apo, Pak. Saya
ndak bisa tenang kalau duduk di
boncengan.”
Akhirnya,
berdua Pak Tungkat, kami lalu menempuh perjalanan keluar masuk perkampungan.
Melewati kebun sawit, jalan setapak yang becek dan berlumpur, naik turun tanah
merah yang berbukit juga beberapa kali melewati semak belukar. Benar kata Pak
Tungkat. Saya harus ekstra hati-hati mengendalikan motor jika tak ingin
tergelincir lalu nyungsep ke permukaan
tanah merah yang masih basah.
“Pak,
berhenti dulu sini.” Saya berseru memanggil Pak Tungkat seraya mematikan mesin
motor. Perjalanan kami sudah berlangsung kira-kira setengah jam. Di sekeliling
kami sekarang, sejauh mata memandang, kebun-kebun sawit tampak terhampar luas.
Padahal wilayah ini masih termasuk kawasan taman nasional Tesso Nilo. Tanaman
palma itu tumbuh di sela-sela tunggul kayu yang menghitam, tampak seperti bekas
terbakar. Ada serakan potongan kayu-kayu kecil di sekitarnya yang juga dalam
keadaan gosong.
“Kenapa
lahan sawit juga dibuka di sini, Pak? Bukankah ini masih termasuk kawasan taman
nasional? Dan sepertinya, ini juga baru dibakar ‘kan?” Saya memberondong Pak
Tungkat dengan pertanyaan sambil mengarahkan kamera ponsel pada sekeliling. Hari
ini saya seperti memasuki areal luas bekas terbakar yang kering dan gersang, bukan
lagi Tesso Nilo yang saya kunjungi tiga tahun lalu. Tesso Nilo dengan pohon-pohon
rimbun khas hutan hujan dataran rendah yang dahan-dahannya seakan saling
bergandengan.
“Begitulah
dik kenyataannyo,” sahut Pak Tungkat.
“Ndak ado pun tindakan tegas untuk perambah-perambah
hutan. Padahal, hari-hari jugo para
petugas melewati jalan ini. Saya akan tunjukkan yang lain lagi. Mari, dik. Kita
naik motor dulu.”
Medan
yang kami lalui selanjutnya ternyata jauh lebih berbahaya. Banyak tunggul kayu
menyembul di jalanan. Jika tak waspada, motor bisa menabrak tunggul lalu terguling.
Pepohonan yang kami temui sepanjang perjalanan, sebagian besar dalam kondisi
merangas. Pak Tungkat menghentikan motornya. Menunjuk ke arah sebuah parit
kecil di jalan menurun.
“Jadi,
sawit-sawit itu nanti akan ditanam di sana?” Saya nyaris berteriak. Di atas
genangan air itu, tampak berderet-deret bibit kelapa sawit yang baru saja
disemai.
Pak
Tungkat hanya mengedik bahu. Tak lagi berkomentar selain membiarkan saya
memotret dari beberapa sudut lalu kembali naik ke motor. Melanjutkan sisa
perjalanan kami yang kian dekat menuju jantung Tesso Nilo.
***********
Seorang
pria yang tengah berdiri di depan sebuah bangunan sederhana, menatap kedatangan
kami dengan mata terpicing. Saya menurunkan masker. Mata pria itu spontan terbelalak.
“Retni!”
Saya mengangguk lalu menghampirinya. “Apa kabar, Pak Salim?”
“Alhamdulillah
baik, nak. Kamu hanya berdua Tungkat?”
“Begitulah.
Tadi saya mengajak teman, tetapi dia sedang sibuk.”
“Iyo, Pak. Berani beno (benar) adik ni naik
motor sendiri. Ndak mau saya
bonceng.” Pak Tungkat berkomentar. “Saya pamit dulu. Keburu malam kalau ndak pulang sekarang.”
Saya
mengucapkan terima kasih pada Pak Tungkat seraya tak lupa memberinya uang
bensin.
“Kita
ke mess saja, nak. Gedung yang ini sedang direnovasi.” Ajak Pak Salim tak lama
setelah Pak Tungkat berpamitan. Sejak dulu, pria ini memang lebih suka menyapa
“nak” pada saya. Sambil melangkah memasuki mess, saya menunjukkan padanya
beberapa foto yang saya jepret sepanjang perjalanan memasuki kawasan Tesso Nilo.
Tak
jauh berbeda dengan reaksi Pak Tungkat, pria ini pun mengedik bahu dan
mengembus napas berat. “Siapo yang
berani melarang mereka, nak. Orang-orang penting semuo yang punyo lahan tu.”
“Lalu,
apa di sini semuanya tetap berlangsung seperti biasa, Pak?” Wajah Pak Salim berubah kelam. Lelaki ini adalah
salah satu pengurus Taman Nasional Tesso Nilo dan telah mengabdikan diri hampir
separuh usianya.
“Dengan
melihat langsung perambahan tadi, menurut nak Retni, apo akan terjadi di sini beberapa tahun lagi? Jangan-jangan kami
pun tak mampu lagi melindungi gajah-gajah itu di sini.”
Ganti
saya yang menghela napas. “Tim flying
squad5), apa kabarnya Pak?”
Flying squad adalah
tim gajah latih di Tesso Nilo. Gajah-gajah jinak ini bertugas mengusir kawanan
gajah liar yang masuk ke pemukiman penduduk untuk kembali ke hutannya. Sejak
dulu, tim flying squad inilah yang
menjalankan operasi rutin di Tesso Nilo untuk mengatasi konflik gajah.
“Momon
yang jadi pimpinan tim flying squad
sekarang. Rahadi mendidiknyo dengan
keras, tetapi penuh kasih sayang. Kamu tahulah bagaimana kalau dia sudah
bersama gajah-gajahnya, bukan?”
Tak
urung, detak jantung saya bersicepat saat nama itu akhirnya terucap juga. Saya
menarik napas dalam-dalam, mengatur kalimat saya tetap tenang saat bertanya. “Di
mana Rahadi sekarang, Pak?”
“Seperti
biasa, sedang bersama gajah-gajah asuhannya. Sejak beberapa hari ini, para
mahout6) di sini bertambah sibuk. Daerah jelajah tim flying squad sudah lebih jauh. Pembakaran
hutan membuat konflik gajah jugo kian
memburuk, nak. Semakin banyak gajah-gajah liar kehilangan hutan dan perlintasan
mereka, lalu masuk pemukiman dan mengganggu penduduk.”
Saya
menarik napas sekali lagi. Dampak pembakaran hutan ternyata membawa masalah
yang lain lagi. Tak hanya masalah kesehatan, tetapi juga keselamatan. Dapat
saya bayangkan bagaimana hutan yang terbakar membuat gajah-gajah liar itu panik,
lalu tak ada pilihan untuk mereka selain menerobos pemukiman penduduk terdekat.
Tugas tim flying squad sudah tentu bertambah
berat, juga para mahout, yang harus mengawal patroli di tengah kondisi udara
yang sangat buruk.
Sesaat,
saya teringat nasib para orang utan di hutan Kalimantan. Saat hutan terbakar,
tak sedikit dari primata langka itu yang menjadi korban. Mulai dari kehilangan
hutan hingga yang ikut terbakar. Belumkah cukup rentetan bencana ini membuka hati
para pelaku untuk berhenti merusak hutan?
“Sekarang
apa kegiatanmu, nak? Masih aktif meliput tentang lingkungan?” Pertanyaan Pak
Salim memecah keresahan saya.
“Masih,
Pak. Sudah sebulan ini, saya meliput tentang pembakaran hutan dan kabut asap.”
“Apa
kedatanganmu kemari juga terkait hal itu?”
“Oh,
tidak. Tapi, bisa juga.”
Ya
Tuhan. Saya menelan ludah. Kenapa saya mendadak gugup? Saya cepat menjelaskan
sebelum lelaki ini telanjur curiga bahwa niat awal saya datang kemari sebenarnya
hanyalah untuk bertemu Rahadi.
“Awalnya
saya tidak punya rencana untuk datang. Tetapi, berhubung hari ini kabut asap
sedikit reda, tiba-tiba terbit keinginan saya untuk berkunjung. Karena setelah ini,
saya juga tidak tahu apakah masih punya kesempatan untuk datang ke sini.”
“Oh
ya? Memangnya, nak Retni mau kemana?”
“Saya
akan....menikah.” Saya memaksa untuk tersenyum. Meski entah kenapa, kata
“menikah” yang terucap dari bibir saya tak ubahnya seolah-olah saya akan
merayakan ulang tahun saja.
“Wah,
selamat ya. Jangan lupa undang saya.” Senyum Pak Salim merekah. “Kapan pestanya,
nak?”
“Masih
lama kok, Pak. Bulan depan insya Allah baru proses lamaran.”
“Rahadi
pasti senang mendengarnya. Sayang, rencana pertunangannya waktu itu gagal.
Kalau tidak, beberapa bulan lagi dia juga mungkin akan menyusulmu.”
“Gagal?”
Saya terperangah.
“Begitulah,
nak. Rahadi bilang dia belum siap. Dia masih ingin mengabdi di sini. Tetapi, apa
alasan sebenarnya, hanya Tuhan dan dia yang tahu. Omong-omong, kamu sudah
makan?”
“Sudah,
Pak. Tadi pagi.” Saya melirik jam seraya memikirkan hal lain untuk segera
mengenyahkan rasa kaget saya terhadap kabar ini. Dulu, Pak Salim juga yang
mengirim kabar pada saya akan rencana pertunangannya. Sedangkan Rahadi, justru
diam seribu bahasa. Jangankan mengabari, ia bahkan tak pernah menjawab setiap
saya mencoba menghubungi. “Bapak tahu rute tim flying squad hari ini?”
“Kenapa?”
Pak Salim balik bertanya. “Kamu mau menyusul?”
“Jika
mungkin, kenapa tidak? Saya ingin meliput aktivitas flying squad agar semua orang tahu bahwa pembakaran hutan tidak
hanya mengancam kesehatan dan nyawa manusia, tetapi juga bencana lain yang tak
kalah mengerikan.”
Pak
Salim terdiam sejenak. Menatap saya sungguh-sungguh. “Saya menghargai niat
baikmu. Tetapi, kondisi udara saat ini membuat sinyal komunikasi jadi lelet.
Sejak hari pertama, kami sulit menghubungi mereka saat berada di lapangan. Apalagi
kalau mereka sudah berada di sekitar hutan bekas pembakaran. Kesehatan para
mahout dan gajah-gajah pun mulai menurun beberapa hari ini. Tetapi, kalau kamu
ingin tahu apa saja yang sudah kami lakukan, berapa jumlah gajah liar yang
berhasil kami giring ke hutan konservasi agar tidak mengganggu penduduk, saya
bisa membantumu.”
“Oh,
baiklah kalau begitu. Saya akan tetap di sini sambil menunggu kedatangan....tim
flying squad.”
Saya
mengembuskan napas lega. Untuk kesekian kalinya, lidah saya nyaris gagal bekerjasama
dengan isi hati saya yang masih dipenuhi keinginan untuk mendentangkan nama
Rahadi.
**********
Singapura,
akhir Agustus 2015
Lelaki
itu mulai resah. Bahkan yang tidak pernah diperhitungkan pun justru membuat
masalah. Tak ada pilihan selain kembali menekan ponsel pintarnya dan menunggu
suara jawaban di seberang sana.
“Kenapa
berita basi itu terekspos lagi?”
Berbeda
dari yang sudah-sudah, kali ini ia merasa tak perlu lagi menggunakan salam
pembuka dan basa-basi. Sedapat mungkin ia menahan volume suaranya agar geramnya
tak sampai kehilangan kendali.
“Mungkin,
mereka memang sengaja memulai dari sana, Pak.... untuk membidik sasaran yang
lebih besar.”
“Siapa
redakturnya?”
“Kita
tak bisa menyentuhnya, Pak. Ada orang kuat dibelakangnya.”
“Kalau
begitu, cari penulisnya. Bikin dia jera.”
“Baik,
Pak.”
***********
Senja telah turun di Tesso Nilo saat dari
kejauhan, saya mendengar lengkingan suara gajah berpadu bunyi mesin mobil yang
menggerung kasar.
Suara
itu, dulu pernah begitu akrab. Bukan hanya karena lengkingnya yang khas, tetapi
juga karena setiap kali saya menghampiri asal suara itu, seorang pemuda dengan
cambang halus dan kulit cokelat terpanggang matahari, pasti juga sedang berada
di sana.
Ya.
Antara Rahadi dan gajah-gajahnya sudah seperti ayah dan para anak balitanya.
Dia biasa tiba di istal7) saat mahout lain masih meringkuk tidur di
dalam mess. Membersihkan istal, menyiapkan rumput-rumput, lalu menyapa
gajah-gajahnya satu per satu. Saya masih ingat, Rahadi punya tiga ekor gajah di
bawah asuhannya : Momon, Alang dan Rimba.
“Mereka
sudah pulang,” gumam Pak Salim. Pria itu bangkit dari kursi dan keluar lebih
dulu. Saya mengekorinya, meninggalkan kursi dan meja yang penuh guntingan koran
dan dokumen berisi data tentang konflik gajah yang terjadi di sekitar Tesso
Nilo pasca pembakaran hutan.
Pak
Salim menghampiri rombongan yang baru tiba itu. Tiga orang pria tampak
menggiring lima ekor gajah dewasa menuju istal. Dua orang tetap tinggal dan sejenak
berbicara dengan Pak Salim. Saya bergeming. Telapak kaki saya seakan langsung
tertancap di lantai teras saat mata saya menangkap kehadirannya.
Dia
tak jauh berbeda dengan Rahadi yang saya kenal tiga tahun silam. Seragam mahout
berwarna biru donker itu membungkus erat tubuhnya, membuat otot-ototnya tampak cekal
dan tegap. Warna kulitnya tampak kian legam. Dia menurunkan maskernya. Menyeka
dahinya dengan punggung tangan. Sementara tangannya yang sebelah lagi membelai
tubuh besar Momon – gajah asuhannya yang paling dia sayangi itu. Tentu saja saya
masih mengingat Momon. Dia satu-satunya gajah latih di Tesso Nilo dengan
telinga berbercak putih dan gading kanan yang sedikit retak.
Saya
masih “menikmati” pemandangan itu saat
tahu-tahu saja lelaki itu memutar kepalanya dan menyadari kehadiran saya.
Bibirnya tampak mengucapkan sesuatu. Rahadi sejenak menoleh pada Pak Salim yang
juga kemudian memutar wajahnya kearah saya.
Saya
maju selangkah. Namun Rahadi bergerak lebih cepat. Sosoknya telah lebih dulu berdiri
menjulang di depan saya dan menghentikan langkah saya.
“Retni...”
Kedua matanya membesar. Menatap saya dengan tatapan tak percaya. Seolah-olah
kehadiran saya di sini hanya ada dalam mimpinya yang tak pernah menjadi
kenyataan.
“Rahadi.
Apa kabar?” Saya tersenyum formil. Di depan saya, lelaki ini menarik ujung
bibirnya, mungkin ia juga mencoba untuk tersenyum. Namun usahanya gagal. Di mata
saya, lengkung bibirnya tampak seperti cengiran pahit.
“Baik.
Hanya situasi saat ini tidak begitu baik. Pak Salim sudah cerita apa saja
padamu?”
“Kurasa,
hampir semuanya. Sungguh, aku tidak sabar untuk menulis semua yang terjadi di
sini. Sepanjang yang kutahu, belum ada media yang meliput tentang dampak
pembakaran hutan terhadap konflik gajah juga perambahan hutan di sekitar Tesso
Nilo.”
“Memang,
sejauh ini belum ada awak media yang sampai kemari. Kau orang pertama,” Rahadi
menatap lekat. Saya cepat memalingkan muka. Tatapan itu, dulu yang pernah
membuat saya terpesona.
“Omong-omong,
kenapa kita masih di luar? Apa paru-paru kalian punya anti asap? Ayo masuk ke
dalam.” Suara Pak Salim memecah suasana yang entah-apa-harus-saya-menyebutnya
diantara saya dan Rahadi.
“Sekarang
sudah maghrib. Kamu menginap di sini, kan, nak?” tanya Pak Salim sambil
melangkah mendahului kami. Pria separuh baya ini, sejak dulu memang kerap
dijuluki Si Langkah Cepat. Saya memandang sekeliling. Senja baru saja
pergi. Gurat langit telah berbias warna kelabu. Tak ada pilihan untuk saya
selain bermalam di Tesso Nilo. (bersambung)




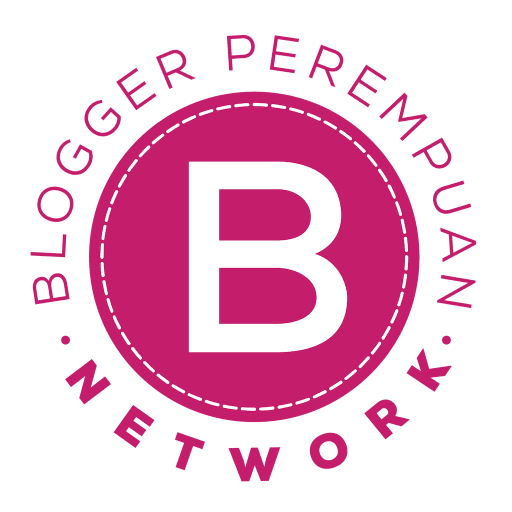










Saya hanya ingin hidup tenang dan tetap bisa bernapas sampai kabut asap ini ndak ado lagi, kutipan ini mengingatkan rokok
ReplyDelete:D
DeleteDi tunggu sambungannya kak
ReplyDeletesudah berapa kali baca tetap ingin baca. tulisannya mantap kak
ReplyDelete"Saya hanya ingin hidup tenang dan tetap bisa bernapas sampai kabut asap ini ndak ado lagi." Memang ungkapan yang sangat menyentuh... Duh kebayanglah kalau aku masih hidup di Pekanbaru yang tiap tahun pasti sengsara saat musim asap...
ReplyDeleteLangganan asap mmg disana sampe gak ada lagi bakar2 hutan
DeleteCeritanya menggugah. Apalagi berkisah kejadian "nyata"
ReplyDelete