Sinopsis :
Mengejar jejak
sebuah email, telah membawa Faras menjelajah satu tempat ke tempat lain. Dari
Borobudur hingga Tanjung Bira. Hanya untuk mencegah luapan dendam sebuah hati
yang merasa memiliki sepuluh alasan untuk membunuh ayahnya.
Namun, dengan
sepuluh alasan pulalah, Raja Ikhsan, sang pendaki tangguh, akhirnya berhasil
menguarkan dendam itu di puncak Mahameru. Dan, di altitude 3676, ketinggian
3676 meter di atas permukaan laut, Raja Ikhsan tak sekedar menjumpai sebuah
ketundukan, tetapi juga beningnya sebuah cinta dan keikhlasan.
Ini adalah satu
dari sedikit novel yang luar biasa. Bagaimana tidak? Dalam rentang waktu yang
berdekatan, novel ini berhasil meraih dua penghargaan nasional sekaligus, yaitu
pemenang dua lomba Novel Republika pada tahun 2012, dan pemenang IBF Awards
2014 untuk kategori fiksi dewasa.
Kali pertama
membaca novel ini dalam versi terbitan Republika yang berjudul Tahta Mahameru,
jujur saja, saya kurang tertarik. Pertama, karena teknis EYDnya yang sangat
mengganggu. Saking ingin taat aturan mungkin, sampai-sampai sebutan “lu” dan
“gue” pun dicetak miring, ini tak termasuk cetak miring untuk kosakata lain
yang bukan berasal dari bahasa baku. Dengan novel yang cukup banyak memuat
dialog, suer deh, mata saya rasanya hampir juling membaca lembar demi lembar
yang bertaburan kata dicetak miring.
Belum lagi minus keterangan waktu dan
diksi oleh pov 1 yang mirip-mirip, membuat saya harus berulang kali bolak-balik
untuk recheck siapa yang lagi
ngomong, dimana lokasi, dan kapan setting
waktunya. Ujung-ujungnya, saya menyerah di halaman berapa, saya lupa. Novel
bersampul warna biru muda itu pun hanya tersimpan di rak buku sampai tahun
berlalu.
Awal tahun ini,
saya dibuat takjub dengan kabar bahwa novel ini meraih penghargaan IBF Award,
dan karena sudah dicetak ulang oleh penerbit berbeda, rasa penasaran saya pun
muncul lagi. Dan ternyata, edisi baru dengan judul Altitude 3676 ini, jauh
lebih bagus dari versi pertamanya. Tak ada lagi lembar-lembar yang penuh dengan
italic word, keterangan waktu juga
dibuat lebih jelas hingga saya tak lagi merasa kebingungan kapan waktu ditarik
maju dan mundur. Suntingan yang lebih rapi juga membuat novel ini menjadi lebih
enak dibaca dan dinikmati.
Diantara semua
unsur fiksi yang terangkum dalam novel ini, tentunya, faktor latar tempatnya
paling layak diacungi jempol. Pengalaman penulisnya yang hobi travelling
tertuang dengan begitu indah, rapi dan detail dalam novel ini, dan tidak hanya
sekadar menyajikan deskripsi tempat, Yana, demikian biasa penulis dipanggil,
juga melengkapinya dengan kultur masyarakat setempat, salah satunya kultur
masyarakat Bugis dan pembuatan pinisi.
Ini juga yang
menurut saya sesuatu yang luar biasa. Mengingat selama ini, kebanyakan penggila
travelling dan backpacker yang bisa menulis, cenderung menuliskan pengalamannya
dalam bentuk buku travelling, sebut saja diantaranya The Naked Traveller-nya
Trinity dan Love Traveller Windy Ariestanty. Namun di sini, Yana justru
menuangkannya dalam bentuk fiksi. Kalau dibilang ini karena Yana memang penulis
fiksi, rasanya kurang beralasan juga, mengingat saya pernah membaca novel karya
penulis lain yang juga lebih banyak menulis fiksi dan hobi travelling, namun
novel berlatar travelling yang ditulis beliau tidak sedetil penuturan Yana dalam
novel ini.
Selain itu,
tentu saja, unsur filosofis, religius dan pencarian kebenaran oleh tokoh utamanya,
alur yang rapi menjadi faktor keunggulan lain dari novel ini. Lantas, kira-kira
faktor yang kurang unggulnya ada dimana ya?
Sebenarnya,
rada-rada sungkan juga sih. Sudah jelas ini novel pemenang
lomba bergengsi, kok ya masih punya faktor kurang unggulnya?
Jadi, apa yang
berikut ini saya tuliskan, anggap sajalah hanya semata-mata faktor selera.
Dari segi
dialog, terasa inkonsisten, kadang gaul, kadang puitis, dan lebih banyak yang terasa kaku. Walaupun ketiga tokoh utama
novel ini – Faras, Mareta dan Raja Ikhsan – digambarkan berasal dari suku yang
berbeda, namun saya kurang mendapatkan nuansa kesukuan yang tercermin lewat
cara mereka berbicara. Saya gagal merasakan kalau Faras itu orang Jawa, saya
juga gagal merasakan feel orang
Jakarta dalam sosok Mareta meski dalam dialognya tokoh ini menggunakan lu dan
gue. Meski demikian, selipan bahasa Bugis dalam dialog keluarga Aros cukup
memberi warna kultur Bugis yang khas.
Alurnya juga
terbilang cukup lambat menuju konflik, diksi Yana yang tidak terlalu spesifik
dan sedikit "longgar", juga membuat beberapa bagian terasa monoton. Untungnya ini
bisa terselamatkan dengan deskripsi latar tempatnya yang detil, indah dan dinamis.
Ada beberapa
kebetulan yang sepertinya menjadi benang perekat dalam cerita ini, seperti pertemuan
Faras dan Mareta disaat Faras memang tengah mencari Raja Ikhsan yang ternyata
juga adalah abang tiri Mareta. Pertemuan Raja Ikhsan dengan Aros yang ternyata
adalah adik Fikri sahabat Ikhsan yang wafat karena mempertahankan adat.
Untuk latar dendam raja Ikhsan, saya pikir, mungkin akan terasa lebih smooth, jika narasi dari pov Ikhsan tidak terlalu banyak, namun lebih fokus pada adegan dan dialog dari kejadian tersebut.
Ada sedikit
inkonsistensi dalam ucapan tertulis Raja Ikhsan dengan karakternya. Di awal
kerap kali disebutkan kalau dia sering terpana bahkan protes, tiap kali
mendengar Faras bicara puitis dan menyebutnya dengan bahasa langit, ditambah
dengan karakternya yang kasar saat bicara, namun di hal. 291-292, terdapat
tulisan tangan Ikhsan di buku tulis yang sangat puitis.
Saya kutip satu
paragraph saja :
Musim
pertanyaan. Sedangkan musim jawaban belum lagi tiba. Masih jauh serupa negeri
di kutub paling dingin di selatan. Dengan apa kujawab sebuah tanya, kalau
burung-burung pun bersembunyi dan tak bisa diajak berbicara.
Selain itu, saya
akui bukan orang yang romantis, jadi sedikit banyak, saya merasa sedikit
terheran-heran ada orang seperti Faras yang hafal banyak puisi Khalil Gibran
dan bisa memosisikan pada momen yang tepat saat berhadapan dengan lawan
bicaranya. Saya pikir, selipan puisi sang maestro ini akan terasa lebih natural
jika tertuang dalam bentuk quote di awal bab atau bahasa tertulis seperti dalam
email-email Faras dan Ikhsan.
Melihat
kriminalitas yang dilakukan Ikhsan terhadap saudara dan ibu tirinya,
jelas-jelas itu tergolong penculikan dan pembunuhan berencana, yang secara
hukum masa pidananya berkisar lima belas hingga dua puluh tahun. Namun di sini,
Ikhsan hanya diganjar dua tahun penjara, itupun masih mendapat pengurangan masa
hukuman atas faktor sogokan sang ayah yang kaya raya. Okelah, anggap saja ayah
Ikhsan memang konglomerat sekelas ARB atau yang lebih dari itu, hingga bisa
membeli hukum di negeri ini dengan uang.
Dan, selayaknya
novel-novel islami yang booming di
era awal tahun dua ribu, novel ini pun masih menampilkan cara serupa dalam
penyampaian pesan islaminya, yaitu melalui sosok “putih” bernama Faras, dengan
semua karakter baik budi pekertinya dan nasehat-nasehatnya kepada Ikhsan, dan inilah
yang mengambil peran penting terhadap perubahan seorang Ikhsan. Mungkin, novel
ini bisa menjadi lebih “menantang” andai metamorfosis Ikhsan lewat kontemplasi,
pengalaman dan perjalanannya jauh lebih dominan ketimbang lewat interaksinya
dengan Faras dan nasehat-nasehat Faras.
Saya yakin,
novel ini pasti menjadi oase buat para penyuka travelling, dengan nuansa
perjalanannya yang sangat kental, indah dan dinamis. Ditambah unsur pencerahan
dan pergerakan tokohnya mengatasi konflik dalam dirinya untuk mencari
kebenaran, serta ending di Puncak Mahameru yang mendeskripsikan Ke-MahaBesar-an dan Ke-MahaTinggi-an Sang Maha Pencipta yang sukses bikin saya merinding, menjadi elemen penting yang membuat novel ini memang layak
juara.
Judul : Altitude 3676 Takhta Mahameru
Penulis : Azzura Dayana
Penerbit : Indiva Media Kreasi
Tebal : 416 hal
Jenis : Fiksi
Terbit : Juli 2013
ISBN : 9786028277921



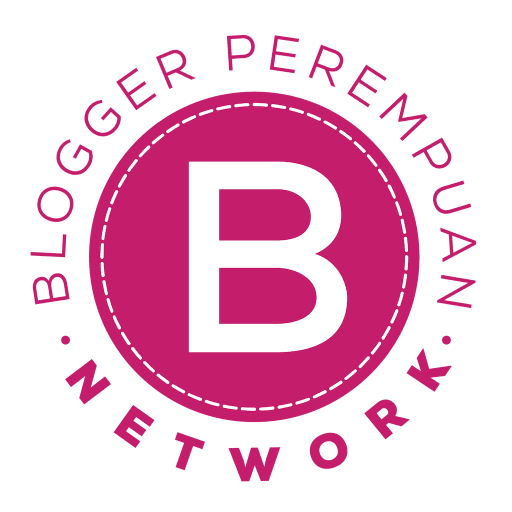










No comments