Apa rasanya saat diri yang masih belia harus mengalami kehilangan beruntun, apalagi kehilangan orang-orang yang dicintai? Ibu yang meninggal dunia, disusul oleh ayah yang sakit jiwa. Inilah yang dialami Rudi, remaja 19 tahun yang hobi bermain sepak bola.
Beruntung, dia masih punya Pak Sadli, guru yang selalu memfungsikan diri bak malaikat pengayom dan penasehat, teman-teman sepermainan yang tetap menerimanya apa adanya.
Namun, semua itu tetap tak mampu mengusir kepedihan di hati Rudi. Kerinduan kerap hadir, mengusiknya dengan kenangan akan masa-masa indah saat ayah dan ibu berada di sisinya.
Mampukah Rudi menghadapi semua itu di usia belianya, ataukah harus kalah dan terpuruk?
----------------------
Entah daya magis apa yang dimiliki novel ini, sehingga sampai menjelang resensi ini saya tulis, saya sudah membacanya hingga tiga atau empat kali. Utuh tanpa skip. Dan setiap kali membacanya, rasa pedih dan pilu yang mengusik hati juga masih sama besarnya.
Ketika saya membaca beberapa ulasan terhadap novel ini, berbilang ulasan menyoroti hal yang sama : tentang fenomena fatherless, penggunaan pov ‘saya’ dan –ku yang inkonsisten dan kadang membingungkan, dan tentu saja lokalitas yang selalu menonjol di dalam novel-novel karya Gegge.
Sepertinya, pengamatan dan penangkapan saya pun tidak terlalu jauh berbeda, namun di sini, saya mencoba mengulas dari sudut pandang yang lain dengan mengangkat sisi-sisi yang “kontradiktif” dari novel ini :
Kontradiktif 1 : deskripsi yang apa adanya, namun tak mengurangi estetika
Adalah hal yang lumrah, ketika banyak penulis berlomba-lomba menggambarkan deskripsi yang indah dan detil dalam novelnya, apalagi saat mengangkat tempat kelahiran sendiri sebagai latar. Namun dalam novel ini, Gegge justru mendeskripsikan latar tempat sebagaimana adanya, tanpa sungkan menceritakan kondisi sesuai realita, seperti deskripsinya berikut ini :
Setiap kamu melintasi kampungku dengan berkendara, jangan coba-coba membuka jendela mobil! Saranku, tutup jendela mobil rapat-rapat lalu nyalakan AC! Jika tidak, maka kamu akan menutup hidung rapat-rapat karena di kampungku banyak orang yang berprofesi sebagai ayam petelur. Kotoran ternak itulah yang kemudian membuat kampungku bau kotoran ayam. (hal. 13).
Dari segi sanitasi, rumah-rumah di perkampungan orang-orang Bugis yang rumah adatnya berbentuk rumah panggung, bisa dikatakan sebagai rumah yang tidak sehat. Kolong rumah panggung biasa digunakan sebagai kandang ayam (hal. 17).
Namun, deskripsi yang realistis ini sama sekali tidak mengurangi estetika dari novel ini. Sebagai penulis yang sudah sering memenangi kompetisi, kemampuan diksi Gegge tak perlu diragukan, sehingga apapun deskripsinya, tetap saja menyimpan pesona. Bahkan saya pun penasaran ingin sekali suatu hari berkunjung ke Sidenreng Rappang.
Sebuah bukti bahwa rasa lokalitas tetap bisa ditonjolkan tanpa harus menampilkan sekadar sisi yang baik dan indahnya saja.
Kontradiktif 2 : plot yang dramatis, namun tetap elegan
Entah pada repetisi yang keberapa, saya baru menyadari bahwa novel ini mengandung muatan plot serbadramatis. Plot yang kalau ditransformasikan menjadi judul sinetron atau FTV di sebuah teve swasta, barangkali akan menjelma seperti ini :
Tetanggaku Ayahku
Guruku Ternyata Abang Kandungku
Cewek yang kutaksir ternyata adikku
Ditinggal wafat ibu dan ayah sakit jiwa
Untunglah, plot-plot ala sinetron ini diolah oleh penulis sekaligus pendidik seperti Gegge. Kepiawaian Gegge berhasil memudarkan kesan “dramatis-komersil” itu menjadi fiksi yang sarat pesan moral dan dituturkan dengan elegan. Gegge tidak mendramatisir plot-plot tersebut dengan cara yang “konvensional”, melainkan memotretnya dari sudut pandang seorang remaja yang untungnya memiliki guru yang bijak serta kepribadian yang cukup stabil.
Gegge tetap menampilkan sosok Rudi secara normal dengan segala kesedihan, luka, kecewa sebagai reaksi atas peristiwa demi peristiwa yang dialaminya, namun Gegge tidak mengeksploitasi sisi emosi Rudi secara berlebihan yang berpotensi dapat menyeret novel ini ke panggung yang sama dengan kisah-kisah yang diwakili judul-judul ala sinetron di atas.
Kontradiktif 3 : fenomena fatherless, tidak selamanya berbuah generasi akhlak-less
Telah banyak teori membahas tentang dampak dari fatherless, salah satunya sebagaimana diungkapkan oleh Sundi dan Herdajani (2013 : 1), bahwa kondisi fatherless dapat berdampak pada rendahnya harga diri, rasa marah, kecemburuan, kesepian, rendahnya kontrol diri, inisiatif, dan sebagainya.
Lebih jauh lagi, kondisi ini dapat berakibat pada penyimpangan-penyimpangan seperti perundungan atau bahkan kecenderungan menyukai sesama jenis.
Fenomena ini beberapa kali saya temukan dalam novel yang mengangkat kondisi serupa, dimana karakter sang anak yang mengalaminya digambarkan sebagai ujud teori-teori tersebut.
Namun, Gegge tidak mengemas teori-teori tersebut untuk menyampaikan pesan akan fenomena fatherless di dalam novel ini.
Teori yang lebih relevan menurut saya adalah hasil penelitian Hurlock (1996 : 205) bahwa remaja pada usia remaja akhir (16, 17 dan 18 tahun) rentan terhadap lingkungan yang mempengaruhi psikologinya. Pada masa ini, remaja akan melakukan penyesuaian diri dengan tugas perkembangan yang baru. Hal ini akan sulit jika tidak ada yang mampu mendampingi.
Di sinilah sosok Pak Sadli dihadirkan sebagai pendamping dan pembimbing Rudi, mengambil alih peran orang tua terhadap Rudi. Gegge mengeksplorasi perkembangan psikis Rudi yang tetap “terjaga” oleh nasihat-nasihat baik di sekelilingnya, terutama oleh Pak Sadli, sehingga meskipun Rudi tetap tak bisa melepaskan diri seutuhnya dari rasa kesedihan, kesepian, dan kehilangan, dia tidak lantas bertumbuh menjadi remaja yang akhlak-less.
Luka, duka, derita, tak menunggu orang dewasa dulu untuk kemudian ditimpanya. Semua kepahitan itulah yang akan menempa kedewasaan (hal. 49).
Quote ini seakan menjadi penangkis terhadap teori-teori yang cenderung “memaklumi” dan “menyepakati” bahwa remaja yang minus kasih sayang dan kehadiran orang tua pasti akan mengalami gangguan psikis atau kepribadian.
Sebagai seorang pendidik, Gegge seakan hendak mengatakan, bahwa tak selamanya masalah hidup akan mengikis sisi positif dan keutuhan seorang remaja, justru sebaliknya, masalah juga bisa menjadi pembentuk kualitas mereka secara alamiah.
Novel ini dikemas dengan alur maju yang diselingi beberapa flashback, dengan karakter utama dipercayakan pada sosok Rudi dan Pak Sadli sebagai karakter pembantu utama yang cukup dominan. Penceritaan berlangsung lancar dengan plot yang cukup rapi. Walaupun bagian tentang pengembalian hadiah lomba foto terasa kurang dieksplor, hal itu tidak terlalu mengganggu keutuhan cerita.
Saya memilih untuk tidak terlalu banyak mengulas unsur-unsur teknis dari novel ini, karena bagi saya, novel Gegge nyaris tidak punya kekurangan berarti dalam hal teknis untuk dikritisi, selain yang sudah saya kemukakan di awal dan telah dibahas serta dikritisi dalam berbilang ulasan sebelum ini.
Novel ini ditutup dengan adegan brilian dan mengharukan, yang secara halus mengetuk kesadaran tentang makna eksistensi orang tua bagi seorang anak. Sebuah novel yang tidak hanya layak menjadi juara, tetapi juga sarat motivasi bagi remaja untuk selalu tegar dan optimis memandang hidup meskipun terbelit masalah dan luka lara, serta mengajak para pembaca dewasa (dan orang tua) untuk lebih memahami bagaimana sesungguhnya wish and need anak dan remaja terhadap orang tua. Karena sesungguhnya, lingkungan masyarakat pun dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang menguatkan para anak dan remaja.
Judul : Ayah, Aku Rindu
Penulis : S. Gegge Mappangewa
Penerbit : Indiva Media Kreasi
Tahun :2020
Tebal : 192 hal
Harga : Rp. 45.000,-



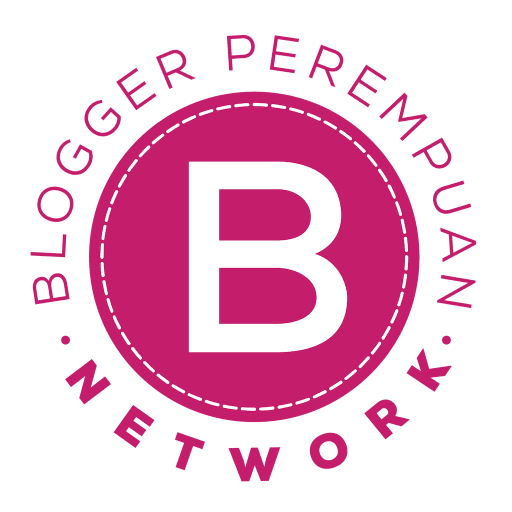










No comments