
Sinopsis :
“Dia korban
perkosaan,” bisikan lelaki berjas putih itu menyakitiku.
Korban perkosaan. Aku mengerang. Meradang. Seakan ingin memapas sosok-sosok beringas yang semalam itu menghempaskan aku kepada jurang kenistaan.
“Kasihan dia,” ujar lelaki itu lagi, samar-samar kutangkap, meski gumpalan salju itu menghalangi seluruh organ tubuhku untuk bekerja normal seperti sediakala.
Korban perkosaan. Aku mengerang. Meradang. Seakan ingin memapas sosok-sosok beringas yang semalam itu menghempaskan aku kepada jurang kenistaan.
“Kasihan dia,” ujar lelaki itu lagi, samar-samar kutangkap, meski gumpalan salju itu menghalangi seluruh organ tubuhku untuk bekerja normal seperti sediakala.
“Kenapa?” tanya
seorang wanita, juga berpakaian serbaputih.
“Rumahnya dibakar. Tokonya dijarah. Ayahnya stress, masuk rumah sakit jiwa. Dan ibunya bunuh diri, tak kuat menahan kesedihan.”
“Rumahnya dibakar. Tokonya dijarah. Ayahnya stress, masuk rumah sakit jiwa. Dan ibunya bunuh diri, tak kuat menahan kesedihan.”
……………
Dalam rencah
badai kehidupan, berbagai kisah indah terlantun: persahabatan, ketulusan,
pengorbanan dan juga cinta. Lewat novelnya ini, Afifah Afra kembali
mengobrak-abrik emosi pembaca lewat novel bergenre fiksi sejarah yang sarat
konflik, diksi menawan dan pesan yang sangat kuat.
Novel ini,
adalah versi cetak ulang dari novel Katastrofa Cinta (KC) yang terbit pada tahun
2008 oleh Penerbit Lingkar Pena. Melintasi masa enam tahun, tentunya, ada
beberapa metamorfosis yang terjadi. Mulai dari sampul, Mei Hwa tampil jauh
lebih lembut, dengan warna biru dan ungu muda, juga membawa unsur filosofis
dari gambar lampion, bunga dan burung.
Bandingkan
dengan sampul KC enam tahun silam yang berwarna “keras” dan kontras,
menampilkan kobaran api yang seolah-olah melukiskan sisi tragis, juga wajah
seorang wanita yang tak jelas mewakili sosok yang mana. Bukan Mei Hwa yang
campuran Tionghoa – Minahasa, ataupun Sekar Ayu yang Jawa - Arab.
 |
| Cover versi Katastrofa Cinta |
Dari segi
kontennya pula, terdapat beberapa sub plot yang mengalami penambalan dan
penambahan, salah satunya pada peristiwa penangkapan dan penyekapan para
Gerwani, termasuklah Sekar Ayu di dalamnya, serta beberapa lintasan peristiwa
sejarah, diantaranya pembayaran pampasan perang oleh Pemerintah Jepang kepada
Indonesia pada tahun 1958, yang di dalamnya konon juga melibatkan para wanita
(hal.149).
Penambahan juga
terjadi pada penekanan akan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa pada kisah Mei
Hwa, yang dalam beberapa dialog, justru sempat menimbulkan kernyitan kecil di
dahi saya.
Pertama – dalam
ucapan Mei Hwa kepada Wibowo. “......Jika kau tak mau disebut sebagai Indon
oleh orang Malaysia, jangan sebut kami dengan Cina...” (hal.72).
Kalimat ini
terasa aneh saat dimaknai dalam dialog. Jika maksud Mei Hwa adalah bahwa
sebutan “Cina” beranalogi dengan indon dalam sebutan orang Malaysia, dan ia tak
ingin disebut Cina, lantas, apa relevansinya saat hal itu diucapkan di depan
Wibowo? Akankah Wibowo bakal dipanggil indon jika ia menyebut etnis China
sebagai Cina? Kenapa tidak langsung saja diucapkan.....”Saat kamu menyebut kami
Cina, maka itu sama saja dengan bagaimana orang Malaysia menyebut orang
Indonesia dengan indon.”
Kedua – beberapa
kali terdapat repetisi akan sikap Mei Hwa yang tak sudi dipanggil Cina. Karena
yang sesungguhnya adalah China. Pertanyaannya, dalam ucapan sehari-hari, apakah
terdengar jelas perbedaan dialektika saat seseorang menyebut Cina dan C(h)ina?
Ketiga –
sebelumnya mohon maaf kalau ingatan saya keliru. Saya memang tidak ingat persis
kapan sebenarnya istilah indon mulai “populer”, mencari di internet pun, tidak
ketemu. Hanya yang berhasil saya ingat, pada rentang waktu 1996-1998, saya
sempat bermukim di negeri jiran dengan populasi TKI cukup banyak, pernah
ngobrol, berinteraksi dengan mereka saat sama-sama mengantri di imigrasi,
pernah juga bolak-balik ke negeri asal muasal istilah indon bermula, bahkan yang paling
tak bisa saya lupa, saat melintasi perbatasan Singapura – Johor di tengah malam
buta, dan dimaki-maki di depan orang ramai oleh petugas imigrasi wanita negeri
jiran, pertama kali saya dimaki dengan sebutan b****b, mungkin karena saya
dikira TKW gelap meski saya membawa dokumen lengkap, tetapi pada masa-masa itu,
telinga saya belum pernah mendengar orang-orang menyebut indon.
Sesuai judulnya, novel ini memang bertutur tentang dua wanita yang hidup pada jaman yang
berbeda. Sosok Sekar Ayu, yang pada masa tuanya kemudian dipanggil mbah Murong,
bersama Mei Hwa, korban perkosaan pada tragedi 1998. Diantara keduanya, memang
terdapat porsi penceritaan yang berbeda. Sekar Ayu adalah wanita pelintas zaman
mulai dari era tahun 1930an hingga tahun 1990an, sedangkan Mei Hwa hanya
mendapat porsi seputar peristiwa tahun 1998. Keduanya bertemu pada satu titik
nadir, saat Sekar Ayu telah hidup terlunta-lunta di usia tua, dan Mei Hwa yang
melarikan diri dari rumah sakit jiwa akibat mengalami gangguan psikis pasca
perkosaan terhadap dirinya.
Dalam hal ini,
tentu saja alur yang melibatkan Sekar Ayu di dalamnya jauh lebih panjang, sarat
lika-liku dan peristiwa sejarah. Untuk menyambung alur cerita yang panjang ini,
penulis memang “mengulurkan bantuan” dengan beberapa narasi akan peristiwa
sejarah yang melintas pada masa itu. Jika saja pergerakan peristiwa yang
terjadi dari masa ke masa yang dialami Sekar Ayu bisa diurai dengan lebih
runut dan teratur, mungkin, novel ini akan menjelma tak kurang tebalnya dengan novel
penulis yang lain yaitu Da Conspiracao (600an hal). Tetapi, jika ini dilakukan, kisah ini mungkin akan berjalan kurang berimbang, mengingat tokoh penuturnya bergantian antara Sekar Ayu dan Mei Hwa, sementara sosok Mei Hwa hanya mewakili masa tahun 1998.
Namun dari segi
penggalian karakter psikis, hal sebaliknya berlaku. Penderitaan yang dialami
Mei Hwa justru lebih tereksplorasi lebih dalam meski sosok yang satu ini hanya
kebagian porsi latar waktu yang pendek dibandingkan pendalaman karakter psikis
seorang Sekar Ayu.
Dan sepertinya
saya menemukan sebuah missing link, saat Sekar Ayu kembali ke Indonesia dari
Jepang, dan ia langsung dapat mengenali kakeknya serta menemukan keberadaannya
setelah 15 tahun tak bersua. Saat pertemuan itu terjadi, usia Sekar Ayu 20
tahun, dan ia terpisah dengan sang kakek saat usianya balita. Apa yang
masih terekam dalam ingatan seorang balita hingga begitu mudah menemukan sosok
tersebut meski telah melintasi masa 15 tahun dan tinggal di negara yang berbeda?
Terdapat dua kebetulan
yang menurut saya cukup “berat”, pertama yaitu pada jalinan yang ada antara
Purnomo – ayah Purnomo – Harada – Sekar Ayu, dan antara Sekar Ayu – Ishihara –
Prakoso. Kedua, pada keluarga Mei Hwa yang ternyata adalah orang-orang yang
pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan Sekar Ayu dan baru diketahuinya
ketika menghadiri pernikahan Mei Hwa. Rasanya, probabilitas terjadinya kebetulan
semacam ini amatlah minim, apalagi melibatkan tokoh di negara yang berbeda, tetapi,
mengingat ini hanyalah fiksi, sepertinya, hal ini tak perlu dipersoalkan terlalu
panjang.
Satu adegan saat
Sekar Ayu jatuh tersungkur di bawah roda kereta di tengah salju (hal.140),
mengingatkan saya pada adegan serupa dalam novel penulis yaitu De Liefde. Dan
ternyata, terjadi perubahan adegan di sini dari versi sebelumnya. Dalam versi KC, adegan tersebut
hanya sebatas Sekar Ayu (Astuti) kecil yang tersesat kebingungan lalu ditemukan
seorang germo.
Tentang
penggunaan diksi, cukup banyak pembaruan liukan metafor yang dilakukan penulis
dalam novel ini. Dengan segenap keterbatasan saya dalam hal membaca diksi, satu
pertanyaan saya, apakah narasi untuk cerita pada masa silam sebaiknya
menggunakan kosakata yang mewakili masa itu, ataukah cukup dilakukan pada
dialog saja?
Saya contohkan
di sini :
“......Mungkin
byte-byte mimpi buruk itu bahkan telah ter-copy pada salah satu neuron, tanpa
aku mampu men-delete-nya. Setiap kali sebuah icon tersentuh, .....” (hal.63).
Ini adalah
narasi pada kisah yang terjadi tahun 1998. Sekali lagi, sependek ingatan saya, pada
masa itu, program komputer yang baru umum digunakan di Indonesia untuk mengetik
adalah MS-Dos, dengan aplikasi yang masih sederhana dan setingkat lebih tinggi
dari mengetik manual, dan beberapa istilah yang di-italic pada narasi tersebut,
baru terasa familier sejak program windows digunakan di tanah air sejak awal
tahun dua ribuan.
Peningkatan
kapasitas metafora dan kalimat-kalimat bersayap dalam novel ini, di satu sisi
memang membuat tampilan novel ini lebih nyastra, “nyeni”, dan sarat ornamen,
namun di sisi lain, hal ini ternyata membawa implikasi pada tereduksinya
kedalaman makna yang sebelumnya berhasil dibangun dengan nyaris sempurna dalam
versi KC.
Saya cantumkan
prolog dari keduanya :
“Seseorang telah
menyulapnya menjadi kayu. Itu yang ia rasakan sejak mendapati dirinya berubah
menjadi seonggok benda kering kaku yang mengerontang di padang gersang. Kini
benda kering itu, yang mungkin pohon dan tak mungkin alang-alang karena tak
pernah ada batang alang-alang mengeras menjadi kayu, hampir roboh, karena
akar-akarnya keropos disantap rayap-rayap beringas. Elannya dipagut sepasukan
elang, hingga muspra, terkapar binasa. Tinggal beberapa desah napas lagi
tersisa......dst (versi KC).
"Seseorang
telah menyulapnya menjadi kayu. Kayu yang kehilangan berat basahnya karena terlalu
lama terpanggang di oven kehidupan. Kayu yang jangankan para penjarah mata
duitan, bahkan rayap pun enggan berlangkan, karena ketiadaan saripati yang
tersisa untuk digerogoti. Menjadi kayu, itu
yang dia rasakan sejak mendapati dirinya pelan-pelan bermetamorfosa sebagai seonggok benda hampa rasa, yang menjelujur kaku serta mengerontang di
padang gersang. (versi Mei Hwa)
Dalam
versi KC, saya dapat merasakan kedalaman dan kekuatan ruh yang mengiringi
setiap baris kata, namun dalam prolog versi Mei Hwa, yang saya rasakan semata-mata
unsur keindahan dan estetika.
Di luar beberapa
catatan di atas, novel ini tetaplah menjadi pembuktian akan kepiawaian
penulisnya mengolah latar sejarah, mengombinasikannya dengan nilai-nilai
idealisme dan religius dalam sebuah fiksi yang berbobot, memiliki “kelas”nya
tersendiri dan menyajikan rangkaian plot dan alur yang rumit dalam cara yang
brilian. Banyaknya tokoh cerita, tak membuat penulis lalai menyertakan latar
belakang mereka, siapa, dan apa kontribusi perannya dalam kisah ini. Bukan hal
mudah tentunya, mengambil intisari peristiwa sejarah yang mewakili setiap
jamannya, melibatkan banyak pelaku di dalamnya dan memosisikan tokoh utamanya
sebagai tumbal perubahan, seperti yang terucap oleh sosok Firdaus pada
hal. 107 : “......Orang China itu banyak yang dijadikan tumbal perubahan.”
Andai premis ini
tidak terucap secara eksplisit, kira-kira, akankah pembaca mampu menangkap
kehadirannya sebagai "pesan" nyata dalam jalinan kisah yang kompleks ini? ataukah ada
pesan lain yang justru lebih kuat terekam dalam ingatan pembaca?
Sekali lagi, salut
dan tabik saya ucapkan untuk penulis. Terlepas dari apapun, novel KC yang
sekarang berubah wujud menjadi Mei Hwa, adalah satu dari sekian novel
inspiratif yang banyak memberikan pembelajaran untuk saya dalam proses menulis,
serta pembuktian bahwa lintasan peristiwa sejarah pun bisa disajikan dalam bentuk fiksi dengan
cara yang menarik, estetis, informatif dan bergizi.
Judul : Mei Hwa dan Sang Pelintas Zaman
Penulis : Afifah Afra
Penerbit : Indiva Media Kreasi
Tebal : 368 hal
Jenis : Fiksi
Terbit : Januari 2014
ISBN : 9786021614112


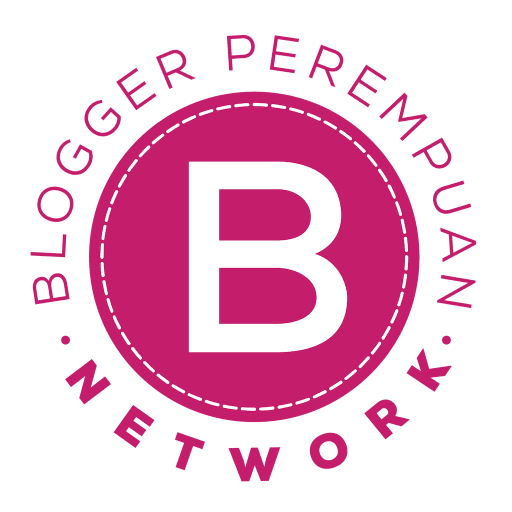










Makasih ya, atas masukan-masukannya...
ReplyDeletecama2, boss :)
ReplyDeletebaru tau kalo ini versi cetak ulang novel yang lama. makasih resensinya, mba
ReplyDeleteWoww..sepertinya ini novel yang berat ya. 'Terbaca' dari review-nya :D
ReplyDeleteBtw, setuju dengan mbak lyta soal pembandingan contoh dua metafora di atas, saya lebih merasakan feel pada kalimat di versi KC dibanding versi Mei Hwa, walaupun saya belum membaca keduanya, hahaa...
Great kakaaa...saya suka reviewmu kali ini ;)
sama2 Ila, iya versi republished KC :)
ReplyDeletemaksaih mbak Eky, ayo di-hunting bukunya, hehe
Pada KC, saya merasa diksinya terlalu tajam, dan bagi sebagian orang, tak terasa nyaman, bahkan mungkin 'kasar'. Jadi, sengaja saya haluskan...
ReplyDelete@Fardelyn: malah di edisi Mei Hwa ini menurut saya nggak seberat KC, lebih ringan.
Oya, mengapa akhirnya bisa ada missing link, sebenarnya konsep awalku, memang pada perjalanan kisah Sekar Ayu lebih ke arah fragmen-fragmen cerita. Jadi memang serba sekilas, tidak dijabarkan detil. Karena, fokus ceritaku kan sebenarnya lebih pada saat pertemuan Mei Hwa dengan Sekar Ayu.
ReplyDeleteNah, soal kebetulan2 itu, aku baru ngeh setelah novel diterbitkan, haha... Mengapa juga namanya mirip, Prakoso dan Purnomo.
Yeni : ketajaman itu sebenarnya kekhasanmu, hehe, dan penghalusan itu sih sebenernya utk estetika it's okay, soal 'ruh' nya, nah itu nggak lihat diksinya halus/tajam sih, tp seberapa besar keterlibatan sisi emosi penulisnya saat nulis. Bbrp novel, malah diksinya biasa aja, tp 'ruh'nya kerasa bgt, cth.nya spt karya2 Dee.
ReplyDeleteYa krn setting di masa lalu, dgn keterbatasan fasilitas n transportasi waktu itu, rasanya memang agak sulit sih memahami perjumpaan sekar ayu dan kakeknya setelah 15 thn gak ketemu yg begitu mudah, tp krn ini fiksi ya sah2 aja sih
review nya bagus...^_^
ReplyDeletemakasih mbak Nita :)
ReplyDeleteSebenarnya sudah disebutkan adanya interaksi bilateral yang menguat antara Jepang-Indonesia, posisi ayah angkat Sekar Ayu yang pejabat di Jepang, ayah Purnomo yang menteri orde lama, serta dukungan pesantren kakek Sekar Ayu kepada partai yang mengusung ayah Purnomo. Itu membuat pertemuan menjadi mungkin dan logis
ReplyDeleteKan di novel itu saya juga menjelaskan tentang harta pampasan perang yang diberikan Jepang kepada Indonesia, serta hubungan para pejabat dua negara yang kian membaik, dan itu secara fakta memang terjadi.
ReplyDeleteKemudian, untuk konteks hubungan china-pribumi, konteks di Jawa dan di Sumatra memang beda. di Jawa, china-pribumi lebih tajam konfliknya dibandingkan dengan china di sumatra/melayu yang cenderung membaur.
ReplyDeleteUntuk pengucapan Cina dan China, coba perhatikan aksen penyiar metro TV yang konsisten mengucap 'Chaina' (China), dan bukan 'Cina', karena Cina sebenarnya identik dengan penghinaan. Kalau group Jawapos, lebih memilih menggunakan kata Tiongkok untuk memuliakan bangsa China.
Nah, kata Indon sendiri, menurut The Encyclopedia Americana oleh Bernard S. Cayne, Robert S Anderson, Sue R Brandt, sudah mulai dipakai tahun 1963. Awalnya tak ada kesan negatif dari kata Indon, tetapi lambat laun mengalami penurunan makna sebagai sifat2 buruk bangsa Indonesia, sehingga secara resmi KBRI memprotes penggunaan kata Indon di media2 Malaysia tahun 2007.
Soal 'ketajaman', saya kira ini soal rasa, soal transfer emosi. Mungkin saat menulis novel ini, tak ada frekuensi yang sama antara saya dengan sebagian pembaca. Memang sebagian yg pernah membaca KC komplainnya begitu, tetapi sebagian justru merasa Mei Hwa lebih halus.
ReplyDeleteoke, makasih jawabannya boss, tp tetep terasa ngeganjal sih ttg sekar ayu bisa kenal kakeknya, hehe
ReplyDeleteBagusnya memang episode Sekar Ayu diuraikan lagi. Jadi, tokoh utamanya adalah Ayu, bukan Mei Hwa. Tetapi, tampaknya Mbak Afra lebih menyukai sosok Mei dan memandang Ayu hanya sekadar fragmen kehidupan.
ReplyDeleteSetelah asyik baca novelnya, lanjut asyik baca resensi :-) Resensinya bagus.
ReplyDeleteBtw, pada tahun 1998, perkomputeran di Indonesia sudah canggih kok. Windows sudah lama ada, internet sudah masuk tahun 1995.