Nah, untuk yang di bawah ini, adalah isi Bab 1 dari novel Hati Memilih (masih dengan judul awal Camelia) yang udah di-cut alias nggak kepake. Yuk yang lagi suntuk boleh baca : :)
----------------------------------------------------------------------
Baru
jam delapan. Malam masih muda. Papa dan mama pada jam-jam ini biasanya baru
tiba di rumah. Lalu mereka berdua akan mengaso
sejenak, dan mama yang kemudian akan menggedor
pintu kamarku untuk mengajak makan malam bersama, dengan hidangan yang mereka
beli saat mampir di restoran cepat saji. Berhubung mamaku adalah wanita karir
yang sangat menghargai quality time, maka
baginya kebersamaan di meja makan jauh
lebih berharga ketimbang menghabiskan waktu dengan bersibuk-sibuk di dapur.
Jika
Ady adik satu-satuku yang super duper aktif itu sedang ada di rumah, maka acara
makan malam kami akan komplit. Masing-masing saling berbagi cerita di meja
makan, tak peduli apakah makanan yang dibeli itu enak atau tidak. Terlalu pedas
atau kemanisan. Terasa asin atau hambar. Pas semua bumbunya atau malah terlalu
ekstrim.
Diantara
kami bertiga – aku, Ady dan papa - hanya papa, satu-satunya makhluk di rumah yang
berani protes jika makanannya kurang enak. Sedangkan aku dan Ady, AMAT SANGAT
jarang melancarkan protes, hingga papa menjuluki lidah kami berdua ‘lidah
buaya’, tak bisa mengenal mana makanan enak dan mana yang tidak. Ujung-ujungnya
papa akan meminta mama untuk memasak sendiri, karena sebenarnya, masakan mama
jauuuh lebih enak.
Tapi
itu dulu. Tepatnya setahun lalu, suasana kehangatan saat makan malam bersama
masih kunikmati, sebelum lembaran putih berstempel Conoco Company itu
‘memerintahkanku’ untuk segera mengepak pakaian dan memindahkan separuh isi lemariku ke
apartemen Paman Fuad.
Bagaimanapun,
aku tetap merasa beruntung. Tidak setiap tahunnya perusahaan gas alam cair itu
memprogramkan beasiswa pascasarjana. Paling banter hanya sebatas bantuan uang
kuliah beberapa semester di perguruan tinggi lokal. Dan bersama dua puluhan
orang yang lolos, kudapatkan
satu kursi magister akuntansi di universitas swasta yang menjalin kerjasama
dengan Conoco itu.
Hm.
Iseng aku memutar-mutar arloji yang terasa longgar di pergelangan tanganku. Tak
terasa, genap setahun, telah kutinggalkan acara makan malam bersama mama, papa
dan juga Ady. Rutinitas yang semula masih kerap menghantuiku dengan rasa kangen.
Apalagi, dalam setahun ini, aku nyaris tak pernah pulang. Meski jarak penerbangan
Jakarta – Tanjungpinang hanya butuh waktu kurang dari dua jam, tetap saja aku
merasa lebih penting untuk berhemat, hemat uang dan hemat waktu. Jadi tak perlu heran kalau masa studi pendek yang
diprogramkan untuk delapan belas hingga dua puluh empat bulan, menjadi
pilihanku saat mengisi formulir paket setelah ujian semester pertamaku
berakhir. Tahu kenapa? Ssst, jangan dulu bilang pada paman Fuad kalau
sesungguhnya aku sudah lama tidak betah, dan berencana untuk pindah ke
kost-kostan saja.
Sebelumnya
kuharap kau mau mendengar ceritaku dulu tentang kebiasaanku untuk nongkrong di balkon.
Di rumahku dulu aku punya balkon persis didepan kamar tidurku. Bentuknya
sebenarnya tidak terlalu istimewa sih. Nyaris tak ada bedanya dengan balkon
biasa. Namun bagiku balkon adalah sepetak ruang privasi yang paling nyaman.
Karena
disana, aku memiliki jendela pandang yang lebih luas saat menikmati suasana di
sekeliling rumah, mulai dari lalu lalang para pejalan kaki, pedagang keliling,
juga sesekali kendaraan roda dua atau empat yang melintasi jalan kecil depan
rumahku. Sedangkan di malam hari, balkon menjadi tempat paling indah bagiku saat
menikmati pemandangan di langit dengan bintang yang berkerlap kerlip dan sang bulan
yang memantulkan cahaya matahari dalam bias warna yang putih lembut.
Ah.
Jangan kau bayangkan aku duduk di balkon bersama pacarku. Aku melakukannya
sendirian saja. Bertemankan alunan instrumentalia yang mengalir pelan melalui iPod,
lalu membiarkan angin malam yang sejuk menerpa dan meredupkan kedua mataku hingga
akhirnya aku sering menemukan diriku terbangun di tengah malam dalam posisi
setengah berbaring dan menyelonjorkan kaki di atas kursi.
Tapi
di apartemen paman Fuad ini, anehnya ukuran balkonnya hanya seupil. Tak sampai
separuh ukuran balkon rumahku. Letaknya didepan ruang keluarga yang disesaki
pula oleh tanaman bunga yang berjejer didalam pot. Tidak ada kursi untuk bersantai,
dan tak seorang pun penghuni apartemen ini yang senang berleha-leha di balkon.
Maka,
aku pun cukup tahu diri dengan menggantikan kebiasaanku itu dengan duduk di
tepi jendela kamar
saja. Kebetulan, ranjang kamar ini persis berada dibawah jendela, jadi hanya
dengan menyilangkan kedua kaki dan meletakkan kedua tanganku di tepi jendela seraya
menumpangkan dagu diatasnya, cukuplah bagiku untuk bisa menikmati pemandangan
diluar sana yang tentu saja jauh berbeda dengan pemandangan depan rumahku dulu.
Paman
Fuad adalah sepupu mamaku, istrinya bernama bibi Salma. Mereka berdualah yang
telah menawariku untuk tinggal di apartemennya saat papa mengabarkan bahwa aku
mendapat beasiswa untuk kuliah di Jakarta.
Sejauh
ini, apa yang bisa kukatakan tentang paman Fuad dan bibi Salma, bahwa mereka sebenarnya
sangat baik. Tapi tidak dengan keempat anaknya yang …. punya tabiat sangat buruk
dan bertolak belakang, juga seringkali membuat ritme jantungku meningkat dan kepalaku berulang
kali menggeleng-geleng meski tak ada suara musik dari headphone yang tengah menyumbat
telingaku.
Tunggu!
Sepertinya aku baru saja melihat sesuatu yang ‘menarik’. Sosok sepasang remaja yang
masih mengenakan seragam putih biru dan berjalan bergandengan saat menyeberang
jalan itu, tentu saja aku mengenalnya. Dia Anita, putri bungsu paman Fuad,
bersama seorang cowok yang juga berseragam yang sama, dan ini bukan kali pertama aku memergoki mereka berjalan
berduaan pada jam-jam begini.
Padahal
usia Anita baru lima belas,
tapi lihatlah! Sekarang ini sudah hampir jam sembilan. Setahuku seorang pelajar
seperti Anita, dengan segala kegiatan ekskul yang seabreg sekalipun, tak semestinya
pulang selarut ini. Tapi pada kenyataannya akulah yang selalu menjejakkan kaki
di apartemen ini berjam-jam lebih dulu jauh sebelum kepulangan Anita.
Kedua
remaja itu berhenti, persis didepan apartemen. Dan remaja pria yang tubuhnya
sekurus tiang listrik itu perlahan membelai rambut Anita lalu mencium gadis itu
– astaga - tepat di bibirnya!
Oke.
Kau boleh bilang aku kampungan. Dan kau juga boleh menganggap kalau itu bukan
lagi pemandangan aneh. Apalagi dilakukan oleh seorang gadis yang dibesarkan di
kota metropolitan. Tapi tetap saja perbuatan
mereka barusan membuatku sesaat tercegat
oleh kekagetan yang akut. Tak pernah ada dalam sejarahnya, papa dan mama
mengijinkanku berkeliaran diatas jam delapan malam dengan masih berseragam
sekolah. Apalagi…berciuman!
Ting
tong! Aku segera meloncat. Itu pasti Anita.
Awalnya aku berniat untuk
keluar kamar saja. Karena aku seringkali merasa tak nyaman jika
harus mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukan Anita setiap kali ia pulang
sekolah. Mencampakkan tasnya begitu saja ke tempat tidur, membuka seragamnya,
lalu membuka dan
menutup lemari pakaiannya dengan cara membanting, terakhir.…menghidupkan
televisi dan memutar musik di
CD player bersamaan! Yeah. Telah setahun
aku ‘menumpang’ di kamarnya,
namun sampai hari ini ia seakan tak pernah menganggap aku ada.
Sampai
hari ini aku bahkan masih dapat menghitung dengan jari berapa kali ia pernah
berbicara denganku. Mungkin saja sesungguhnya ia merasa kesal atau muak dengan
kehadiranku. Merasa tak rela saat satu bagian rak dari lemarinya harus ia sisihkan untuk berbagi denganku. Atau karena
privasinya yang menjadi sedikit terusik saat aku juga tengah berada didalam
kamar. Satu yang pasti, aku tak pernah sudi berbagi ranjang
dengannya. Lebih baik aku tidur di lantai, diatas extra bed yang kutarik setiap malam dan kudorong kembali ke kolong tempat tidur di pagi
harinya.
“Anita,
darimana saja kamu? Malam sekali baru pulang?” Aku mengurungkan niat untuk keluar kamar.
Suara paman Fuad terdengar lantang dan nadanya juga sama sekali tidak ramah. Kebiasaan
Paman Fuad kalau sudah marah-marah, mengerikan! Sekurang-kurangnya kau akan mendengar
lebih dari tiga kali bunyi barang yang pecah karena dibanting ataupun
dilemparkan ke dinding. Dan dari volume suaranya barusan, firasatku mengatakan
bahwa malam ini gendang telingaku akan kembali mendengar bunyi sesuatu yang pecah.
Aku
tak mendengar jawaban Anita. Ia pasti tak berani menatap mata papanya yang saat
marah akan mengilat seperti belati.
Selanjutnya apa yang terdengar adalah suara paman Fuad yang terus meningkat, mengeras,
bahkan sesekali berteriak. Aku tak begitu jelas mendengar semua yang ia katakan, tapi telingaku sempat
mendengar ucapan ‘gadis liar’, ‘anak nakal’, ‘bunting’, ‘memalukan’, lalu ….praangg!
Bunyi pecahan pertama.
Tak
perlu menunggu lama untuk mendengar bunyi susulan berikutnya. Pecahan kedua,
ketiga, terakhir…kudengar suara Anita yang mengaduh kesakitan. Mungkin saja Paman
Fuad sudah menampar atau memukulnya dengan keras.
Pintu
kamar terbuka, didorong oleh kekuatan penuh hingga membentur dinding dan Anita
yang masuk dengan terisak. Aku masih bergeming saat Anita kemudian membuka
lemari, meraih kimononya dan berlari keluar.
Sampai
sekian menit berlalu akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari kamar. Diluar
gelap. Lampu di ruang keluarga mati total. Aku tak bisa melihat apa-apa juga siapapun.
Ini sudah menjadi kebiasaan Zai, anak tertua paman Fuad saat ia ada di rumah
untuk memadamkan semua sumber penerangan hingga aku pernah menyangkanya seorang
yang sangat terobsesi dengan suasana magis. Satu-satunya sumber cahaya saat ini
adalah lampu yang bersinar kuning redup dari arah dapur.
Aku
meraba dinding dan menekan saklar. Tampak olehku Zai yang tengah berselonjor di
sofa dengan mata memerah. Warna mata yang menyerupai mata ikan busuk itu selalu
membentuk asumsi di benakku bahwa pemiliknya tengah mabuk ataupun baru mengonsumsi
sesuatu yang membuatnya serasa terbang ke nirwana. Tak kulihat paman Fuad.
Mungkin sudah pergi atau masuk ke kamarnya. Terdengar suara shower dari arah kamar mandi yang letaknya
persis di sebelah dapur. Itu pasti Anita.
Apa
yang harus kulakukan sekarang? Berada di luar ataupun kembali masuk ke kamar,
keduanya adalah pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan. Tak terbayang olehku
bagaimana harus berpura-pura tidur dengan seorang gadis belia yang tengah
tersedu-sedu di ranjangnya seraya menyumpah serapah papanya atau justru
menyetel volume CD playernya
keras-keras seperti yang selama ini sering ia lakukan saat usai dimarahi
habis-habisan.
Sementara
makhluk bermata merah itu – Zai - belum
juga beranjak dari sofa. Ia bahkan meraih remote
dan menghidupkan televisi. Dalam kebingungan hendak kemana aku menyeret langkah
menuju dapur. Mengambil sebotol air dingin dari dalam kulkas, menuangnya ke
dalam gelas lalu meneguknya sampai tandas.
“Mana
dia?” Aku menoleh. Bibi Salma melongokkan kepala dari balik sekat dapur sebelum
menampakkan diri seutuhnya didepanku. Ia mengenakan daster dan mengikat rambut
ikalnya tinggi-tinggi. Pertanda bahwa ia tengah berada di kamar, mungkin juga
tengah bersiap-siap untuk tidur sebelum peristiwa lemparan ‘UFO’ berupa
piringan kaca yang melayang lalu pecah berkeping-keping saat menghantam dinding
itu terjadi.
“Siapa,
bi? Anita?” tanyaku, nyaris berbisik. Bibi Salma mengangguk. Aku menunjuk ke arah
kamar mandi. Bibi Salma mendengus. “Biarkan. Anak itu memang bebal. Sudah
berkali-kali dimarahi, tetap juga tidak mempan.” Ucap bibi Salma lalu meraih
botol yang sama dan menuang isinya yang tinggal separuh ke dalam gelas.
Aku
perlahan menarik kursi. Lampu di ruang keluarga telah kembali padam. Pasti Zai
yang sudah mematikannya. Bunyi pintu kamar mandi yang digeser diikuti dengan
Anita yang melangkah keluar tanpa menoleh padaku dan bibi Salma, membuat suasana
redup ini sesaat terasa membeku di udara.
Brak!
Kebekuan terpecah oleh bunyi pintu yang dibanting sangat keras. Diikuti oleh
teriakan Zai yang memaki Anita.
“Kupikir
sebentar lagi aku akan gila! Karena hampir semua penghuni rumah ini memang
sudah begini,” ujar bibi Salma, sinis dan lantang seraya menyilangkan
telunjuknya pada kening.
“Lihatlah!
Yang satu hobinya mematikan lampu saja. Tak peduli kita tengah ada di rumah,
tengah mengobrol atau menonton televisi. Yang seorang lagi menganggap rumah seperti
hotel, datang hanya untuk mandi, makan dan tidur (ini omelan bibi Salma tentang
putra kedua, Zein, yang memang paling jarang terlihat batang hidungnya), dan si
perempuan pula, masih ingusan tapi tabiatnya sudah seperti betina jalang!”
Kalimat
terakhir bibi Salma yang terucap dalam nada ketus itu membuat tarikan nafasku berhenti
sesaat. Lidahku pun ikut menjadi kelu sehingga tak bisa berkata apa-apa selain
hanya diam. Perlu kujelaskan disini kenapa bibi Salma sampai bicara sekasar
itu. Karena ketiga anak manusia yang baru saja ia ceritakan dengan raut
setengah frustasi itu, tak lain adalah anak-anak paman Fuad dari hasil pernikahannya
yang terdahulu. Sejak pertama kali datang ke apartemen ini, seingatku mereka bertiga
memang jarang sekali bersikap sopan, apalagi menghargai bibi Salma. (Oh ya, bibi
Salma juga telah memiliki seorang anak sebelum menikah dengan paman Fuad,
namanya Aida. Tentang Aida, akan kuceritakan kemudian).
“Dan
kau lihat? Papa mereka sendiri tak kurang bebal! Bukankah hampir setiap malam
anak gadisnya itu pulangnya malam terus, tapi yang bisa ia lakukan hanya memarahi
dengan membabi buta! Lalu keesokan malamnya hal yang sama terulang lagi,
dimarahi lagi. Hah! Sampai kapan mau begitu terus?”
Bibi
Salma bangkit dari duduknya, membilas gelas minumnya di wastafel lalu
meletakkannya kembali ke rak piring. “Kuharap kau jangan terlalu peduli. Dari
dulu juga sudah begini. Beberapa kali aku mencoba menegur, aku malah diadukan
anak-anak nakal itu pada ibunya. Mereka bilang aku ibu tiri yang jahat. Tapi
yang kuherankan, tak satupun dari mereka mau tinggal bersama ibunya.
Jangan-jangan, ayah tirinya jauh lebih galak dan menyeramkan daripada aku,
hehe.”
Bibi
Salma tertawa. Tak tampak lagi rona kemarahan di wajahnya. Memang, jika sudah
mengobrol ataupun menumpahkan isi hatinya didepanku, bibi Salma biasanya akan
kembali tenang, dan ia tampak merasa lebih senang bila aku ada di rumah.
Mungkin, karena selama ini bibi Salma justru mengalami kesulitan pada saat
mencoba bicara ‘baik-baik’ dengan para trouble
maker itu, bahkan bibi Salma juga jarang ngobrol dengan Aida.
Tentang
Aida – ah - menyesal sekali aku harus berkata jujur, bahwa putri tunggal bibi
Salma ini, tabiatnya pun sesungguhnya tak jauh beda, bahkan dalam beberapa hal
ia justru lebih parah dari Anita. Sepasang kakinya yang langsing dan selalu
bergemerincing oleh bunyi rantai itu baru akan menjejakkan bayangan tubuhnya di
muka pintu apartemen justru disaat semua penghuni rumah telah terlelap dan
kegelapan telah sepenuhnya menyelimuti hari.
Pernah
sekali, iseng-iseng kutanyakan pada bibi Salma mengapa Aida pulangnya larut
malam terus, bibi mengatakan bahwa selain bekerja Aida juga masih melanjutkan
kuliahnya di kelas karyawan yang jadwalnya khusus pada malam hari. Selain itu
juga, karena Aida paling malas bertemu paman Fuad. Ya. Aku sendiri menyadari
bahwa paman Fuad selalu memasang raut cemberut jika Aida ada di rumah bahkan
jarang sekali mau mengajaknya bicara.
“Masih
mau disini, Cha? Aku mau ke kamar dulu. Sudah ngantuk!” ujar bibi Salma seraya
mengisi satu mug besar dengan air dingin untuk ia bawa ke kamar. “Ya, bi.
Sebentar lagi aku juga mau masuk.” Jawabku.
Sepeninggal
bibi Salma, aku kembali menuju kamar, tapi cepat berbalik lagi ke dapur saat
dari balik pintu kamar kudengar suara musik dari CD player tengah diputar dengan volume yang sangat dahsyat. Entah seperti apa gerangan kekuatan suara itu
didalam kamar. Tidakkah Anita khawatir kalau gendang telinganya bisa saja
kehilangan sensitivitas dan mendadak tuli?
Dan…bagaimana
bisa kedua mataku terlelap di tengah keributan semacam itu? Satu hal lagi untuk
kau ketahui, bahwa Anita, tergolong SANGAT parah dalam menjaga etika dan
perasaan orang lain. Mungkin, itu disebabkan perceraian orang tuanya disaat
usianya masih butuh bimbingan dan perhatian, atau mungkin juga, karena
sebenarnya ia memang tak sudi sekamar denganku dan Aida, tapi, seharusnya ia masih
cukup waras bukan? Untuk setidaknya mengecilkan volume musik dan mematikan
televisi disaat aku akan tidur atau bahkan sedang sholat?
Lantas,
bagaimana sekarang? Ikut menonton televisi bersama makhluk bermata merah yang
hobi memadamkan lampu itu? Kurasa, ini alternatif yang lebih mengerikan. Siapa
bisa menjamin kalau mata merah Zai hanya disebabkan ia kurang tidur dan bukan
atas sebab yang lain?
Segera
kutepis dugaan buruk yang mencoba berputar-putar di benakku sebelum dugaan itu
membuatku bergidik. Bagaimana kalau mencari kesibukan saja di dapur? Kesibukan
yang kumaksud tentu saja bukan acara beres-beres, karena dapur apartemen ini
sudah sangat bersih dan rapi. Melainkan mencari kesibukan untuk menentramkan rongga
dalam perutku yang telah kembali berteriak minta diisi.
Aku
lalu mengambil buah apel dan pear dari dalam kulkas. Mengupas dan memotongnya seukuran
dadu serta menyiramnya dengan plain
yogurt. Lalu kuambil garpu, menusuknya satu demi satu, lantas mengunyahnya pelan-pelan
seraya merapatkan bibirku seakan-akan aku
tengah melakukannya didepan kamera untuk sebuah iklan produk pelangsingan tubuh.
Dari dulu sudah begini.
Berapa tahun sudah bibi Salma menjalani pernikahannya dengan paman Fuad, ya?
Aku tak pernah tahu. Mama juga tak pernah cerita. Hm. Pernikahan terkadang menjelma
begitu rumit. Dan betapa sabarnya bibi Salma menjalaninya selama ini.
Sedangkan
aku, jujur, belakangan ini staminaku rasanya terus menurun. Aku jadi gampang
pusing dan mengantuk. Semua pakaian yang kubawa sudah longgar semua. Oke. Aku
memang tetap makan tiga kali sehari. Bedanya, disini aku jarang sekali makan
nasi. Lengkap dengan lauk pauk dan sayuran yang dulu selalu tersaji secara rutin
di meja makan rumahku. Ritme hidup kota metropolitan yang bergerak cepat
akhirnya mempengaruhi alternatifku dalam memilih substitusi lain yang lebih
praktis.
Tapi
tetap saja tak menutup kemungkinan, bahwa masih ada faktor lain yang turut
mempengaruhi perubahan itu. Maksudku, jika hanya sekadar mensubstitusi apa yang
kita makan, itu tak seharusnya langsung menurunkan berat badanmu secara
drastis, bukan? (believe me, I’ve lost 7
kg in a year!).
Jangan-jangan,
suasana serba aneh di apartemen ini membuatku mengalami stress ringan tanpa aku
benar-benar menyadari. Biarpun ringan namun efeknya ternyata paling cepat
menyerang metabolisme tubuh dan kesehatan lambung.
Untuk
kau ketahui, semua kejadian aneh yang kusaksikan di apartemen ini, tak pernah
sekalipun terjadi didalam keluargaku. TIDAK SEKALIPUN. Bahkan terhadap Ady yang
luar biasa jail dan hobi mengisengiku itu pun, aku tak pernah sampai memakinya
dengan kasar, apalagi memukul, meski kemarahanku padanya sudah sampai di
ubun-ubun.
Papa
dan mama – seingatku - tidak pernah benar-benar
bertengkar dihadapan kami. Betapa pintar mereka menyembunyikan permasalahan
dan mengkondisikan suasana di rumah tetap senyaman biasa. Sesibuk apapun itu, mereka
pasti menyempatkan diri untuk menikmati makan malam bersama aku dan Ady.
Memanfaatkan waktu yang singkat namun penuh kehangatan itu untuk saling berbicara,
bertukar pikiran dan mencurahkan uneg-uneg atas segala persoalan yang kami alami
sepanjang hari itu.
Bisakah
kau bayangkan itu? Dan wajar rasanya bukan? Jika aku telah lama menimbang-nimbang
untuk pindah? Ya. Pindah. Secara diam-diam, tanpa sepengetahuan paman Fuad dan bibi
Salma, sejak seminggu ini aku sudah bergerilya mencari kost-kostan yang tidak
terlalu jauh dari kampusku.
Potongan
terakhir buah pear meloncat masuk ke mulutku persis disaat Zai masuk ke dapur
lalu menuang susu coklat ke dalam gelas bersama bongkahan es batu. Aku paling
benci kalau para trouble makers ini tengah
mengeluarkan es batu dari tempatnya. Karena bunyinya pasti ribut sekali. Seakan
ada sekarung batu-batu kerikil tengah dituangkan ke atas lantai. Padahal
pekerjaan sesederhana itu, sesungguhnya bisa mereka lakukan tanpa perlu mengeluarkan
suara berlebihan bukan? Ah. Dasarnya pemicu keributan. Menuangkan es batu saja
sudah memekakkan telinga dan membuat kesal setengah mati.
Segera
kutinggalkan dapur, setelah mencuci piring buahku di wastafel dan meletakkannya
kembali di rak. Syukurlah, lampu kamar Anita sudah redup. Tak ada lagi suara
musik yang terdengar sampai keluar. Aku mendorong pintunya dengan hati-hati dan
mendapati Anita yang sudah tidur tertelungkup bersama ponsel yang masih
tergenggam erat di tangannya.
Aku
lalu menarik extra bed dari kolong tempat
tidur. Dalam sekejap aku sudah bergelung dibalik selimut. Angka 18’C adalah
angka favorit Anita untuk suhu pendingin ruangan, lalu dengan ‘kejam’nya ia
akan menyimpan rapat remote pengontrolnya
dibawah bantal. Membuat tulang-tulang yang bersembunyi dibalik kulitku seakan
tertusuk dengan tajam, oleh dingin yang menelusup dari permukaan lantai juga
dari hawa yang berhembus dari kotak pendingin ruangan.
Rasanya
aku baru saja terlelap saat telingaku mendengar bunyi pintu yang didorong. Meski
kelopak mata terasa berat, kuturunkan juga selimutku untuk mengintip. Dan sepasang
kaki jenjang itu, yang berbunyi gemerincing setiap kali ia melangkah oleh rantai
emas mungil yang melingkari pergelangan kaki kanannya, tampak terburu saat
masuk ke kamar dan langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Itu Aida. Dan
itu berarti, bahwa saat ini sudah lewat tengah malam.
Tapi…Masya
Allah! Apa ini? Hidungku mendadak sempit. Ya. Indera penciumanku tak mungkin
salah. Ini bau minuman alkohol. Sangat tajam dan menusuk. Mengekspansi kamar
sempit ini dan nyaris tak menemui celah untuk lolos.
Aku
spontan bangkit dan duduk. Bau alkohol itu, jelas berasal dari tubuh Aida.
Lebih tepatnya, dari arah mulutnya yang menganga sementara posisi separuh
kakinya menjuntai hampir menyentuh lantai.
Sesuatu
terasa mendesak keluar dari rongga mulutku. Aku segera melempar selimutku dan membuka
pintu. Aku yakin ini bukan pertama kali Aida pulang dalam keadaan mabuk. Aku
sudah sering menemukan tubuhnya di pagi hari dengan masih belum menanggalkan
pakaian terakhirnya dan menggeletak begitu saja di sebelah Anita. Tapi baru
malam ini, aku masih terjaga disaat ia pulang.
Kulihat
lampu dapur menyala terang. Sayup terdengar bunyi orang sedang memasak. Siapa pula
gerangan yang sibuk-sibuk di dapur tengah malam begini? Ini kan bukan bulan
puasa?
Sekali
lagi, aku sangat kaget. Meski tidak sekaget sebelumnya ketika bibi Salma
menyebut Anita betina jalang. Di dapur, tampak Zai tengah mengiris-iris bawang
diatas talenan. Tapi Zai tidak sendirian. Ia ditemani Lilian. Kekasih barunya
yang kulihat rajin sekali bertandang kemari sejak akhir-akhir ini.
Aku
tak melihat Lilian sebelum meninggalkan dapur beberapa jam lalu. Lantas, jam
berapa dia datang? Atau, jangan-jangan Lilian sudah ada di kamar Zai ketika paman
Fuad memarahi Anita.
“Belum
tidur?” tanya Zai saat menyadari kehadiranku. “Belum. Mau ke toilet.” Jawabku,
seraya mengerling ke arah Lilian. Gadis berwajah oriental itu tersenyum padaku.
Aku tidak membalas, hanya mengangguk. Karena saat ini aku tengah sekuatnya
menahan rasa mual, ingin muntah dan sakit perut yang muncul bersamaan.
Membuatku sedikit tergesa saat menarik pegangan pintu kamar mandi, lalu….huekk!
Huh.
Aku mengusap peluh yang mulai mengembun di keningku. Kenapa ‘musibah’ ini harus
terjadi sekarang? Setelah bertahun-tahun lamanya lambungku tak pernah sekalipun
bertingkah aneh-aneh namun kini ia harus mengeluarkan semua isinya hingga tak
ada lagi yang tersisa selain hanya berupa cairan bening? Dan… kenapa harus
berlangsung ditengah canda tawa dua sejoli yang sedang memasak bersama hanya
dalam jarak beberapa meter saja dari kamar mandi ini?
“Hm, clever….”
“…….delicious.” “Ups, the smell
is good!” Dan masih ada sederet pujian spontan
meluncur riang dari bibir Lilian ditingkahi bunyi spatula yang memukul wajan berbaur
desis minyak goreng. Aku memijit-mijit tengkukku, juga mengelus-elus perutku
yang semakin dielus justru semakin melilit. Baru teringat kalau sepanjang malam
tadi, aku hanya mengisi perutku dengan selapis sandwich dan potongan buah keras
bersiram saus dingin. Ditambah dengan sengatan aroma alkohol yang mengekspansi
habis indera penciumanku juga saluran pencernaanku. Lengkap sudah semuanya. Aku
nyaris limbung saat keluar dari kamar mandi.
“Hey,
kamu sakit ya? Wajahmu pucat sekali.” tegur Lilian heran. Aku menggeleng lemah.
“Tidak. Hanya masuk angin. Sebentar juga sembuh.”
“Perlu
obat?” Kali ini giliran Zai yang bertanya.
“Tidak.”
Aku menggeleng lagi. “Tapi…boleh aku pinjam…pewangi ruangan?”
Zai
dan Lilian saling tatap. Wajah mereka saling memancarkan kebingungan.
Cepat-cepat kujelaskan, “Ada bau kurang sedap di kamar Anita. Tapi Anita, juga
Aida sudah tidur. Mudah-mudahan setelah disemprot, baunya bisa hilang.”
Zai
mengangguk-angguk. “Tunggu disini, biar kuambilkan.”
“Eh,
tidak usah, biar aku saja. Nanti omeletmu hangus. Dimana letaknya?” Lilian
cepat menyela. “Diatas lemari pakaian, disamping buku-buku tebal milik Zein.”
Sepeninggal
Lilian yang segera menuju kamar Zai, aku duduk di kursi dengan perasaan
canggung. Membayangkan seorang gadis masuk ke kamar pacarnya malam-malam buta
begini, bulu kudukku langsung berdiri, apalagi jika suatu hari nanti melihat
mereka tidur bersama seperti yang pernah dipergoki bibi Salma? Wajar saja kalau
bibi sering mengeluh.
Zai
telah selesai dengan omeletnya. Lalu meletakkannya diatas piring datar. “Kamu
mau?” tawarnya. Aku menggeleng. “Tidak. Terima kasih.”
“Itu
pasti si Salju yang sudah pipis sembarangan. Anita memang pemalas. Tidak pernah
lagi mengajari si Salju untuk membuang kotoran ke kamar mandi.” Ujar Zai,
berulang kali menyebut nama si Salju, kucing peliharaan mereka yang adalah
campuran antara kucing Angora dan kucing domestik.
“Itu
bukan bau kotoran kucing. Tapi bau….” Ups! Hampir saja aku keceplosan, menyebut
bahwa itu tak lain adalah bau minuman beralkohol. Untung, disaat bersamaan
Lilian muncul di pintu dapur dengan menggenggam sebotol pewangi ruangan dan
memberikannya padaku. “Terima kasih.” Ujarku, lalu cepat-cepat meninggalkan
dapur.
Sesampai
di kamar, aku segera menyemprotkan pewangi itu secara merata ke setiap sudut. Termasuk
menyemprotnya juga ke tubuh Aida. Peduli amat. Toh Aida dan Anita, masih sama
pulasnya.
Aku
lalu meletakkan pewangi ruangan itu didepan pintu kamar Zai. Meski aku tahu bahwa
pintu kamar Zai tidak terkunci, tapi aku tidak mau masuk ke dalam, seperti
Lilian. Sama sekali diluar kebiasaanku untuk nyelonong masuk ke kamar orang
lain tanpa minta ijin terlebih dulu.
Perlahan
kurebahkan tubuhku diatas kasur seraya menarik nafas dalam-dalam. Aroma alkohol
perlahan tersingkir oleh wangi lavender. Namun tidak demikian halnya dengan
pikiran kusut yang masih saja berputar-putar didalam benakku. Kedua mataku,
sialnya turut sepakat untuk enggan terlelap. Entah telah berapa menit
terperangkap dalam buntu dan kebimbangan, sampai akhirnya kudengar bunyi pintu
depan yang dibuka lalu ditutup dan dikunci. Itu pasti Zai dan Lilian. Sekali
lagi bertingkah anomali dengan bepergian di tengah malam buta.
Aku
menghela nafas. Berusaha memejam mata dan mengosongkan pikiran. Namun
kesadaranku tak segera sirna saat satu demi satu adegan itu kembali
berseliweran. Anita, berciuman, piring
pecah, Zai dan Lilian, Aida…..
Keputusanku
bulat sudah. Setahun, rasanya tak mungkin untuk bertahan lebih lama dari ini. Aku
harus segera pindah. ASAP.


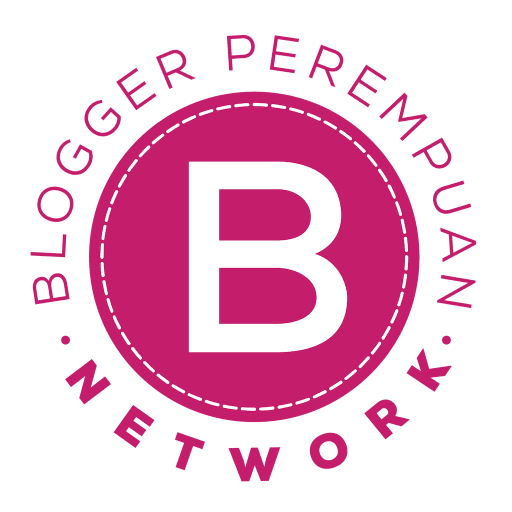










kenepong kok dibuang mbak ? ini kan bagus bangett...
ReplyDeleteya ituu, krg efektif, hehe
ReplyDeleteKunjungan pertama di rumahmu mb :) Dicut sepanjang ini? Memang lbh enak yg versi setelah revisi ya mb hehe.
ReplyDeletemakasih mbak vanda dah mampir, iya, lebih enak yg vrs pasca revisi, ini masih mentah bgt yak :)
ReplyDelete